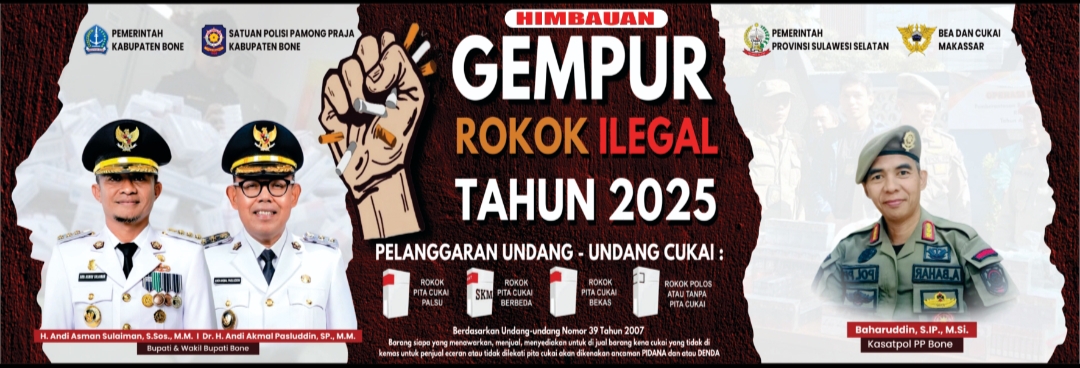Oleh: Prof. Syaparuddin
Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
——————
KETAHANAN pangan dalam Islam merupakan konsep fundamental yang tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Dalam perspektif Islam, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur’an menegaskan bahwa segala yang ada di bumi diciptakan untuk kemaslahatan manusia, termasuk sumber daya pangan. Hal ini tercermin dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk memakan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan-Nya. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep halal dan thayyib, yang menuntut keterjaminan kehalalan, kebersihan, serta kebermanfaatan bagi kesehatan dan kehidupan manusia.
Secara konseptual, ketahanan pangan dalam Islam merupakan bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar yang halal, baik, dan bermanfaat. Ketahanan pangan tidak hanya dipahami dalam kerangka ketersediaan fisik, tetapi juga dalam konteks akses yang merata dan pemanfaatan yang bijaksana. Al-Qur’an mengajarkan bahwa segala rezeki yang Allah sediakan di bumi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga pangan menjadi sumber kehidupan yang mendukung keberlangsungan manusia tanpa menimbulkan ketimpangan dan kerusakan. Konsep ini menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari ibadah, karena pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syariah yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kemaslahatan masyarakat luas.
Prinsip ketahanan pangan ini erat kaitannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) dan hifz al-māl (pemeliharaan harta). Pemeliharaan jiwa membutuhkan asupan pangan yang memadai untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sementara pemeliharaan harta menuntut agar sumber daya pangan dikelola secara efisien dan tidak dihambur-hamburkan. Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa pangan bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dipelihara. Ketahanan pangan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pangan yang layak sesuai dengan ketentuan Allah.
Al-Qur’an memberikan banyak arahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk pangan, agar tidak dilakukan secara berlebihan atau menimbulkan kerusakan. Dalam Surah Al-A‘raf ayat 31, Allah melarang umat manusia untuk bersikap israf atau berlebihan dalam konsumsi, karena perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan ketersediaan pangan di masa depan. Larangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan pangan merupakan prinsip utama yang harus dipegang oleh umat Islam. Dengan menjaga pola konsumsi yang moderat, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhannya secara layak, tetapi juga melindungi hak generasi mendatang untuk memperoleh pangan yang cukup.
Moderasi dalam konsumsi yang diajarkan Islam juga berlaku dalam konteks distribusi pangan. Ketahanan pangan yang berkeadilan tidak mungkin terwujud jika akses terhadap pangan hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk eksploitasi yang merugikan kepentingan umum, termasuk praktik penimbunan (iḥtikār) yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat kecil. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang mengutuk tindakan penimbunan karena menimbulkan kesulitan bagi umat. Ketahanan pangan yang Islami harus memastikan distribusi yang adil dan mencegah praktik-praktik yang mencederai keadilan sosial.
Selain itu, ketahanan pangan dalam Islam menekankan pentingnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pangan tidak boleh diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya tanpa memperhatikan kelestariannya. Islam mengajarkan bahwa bumi adalah amanah yang harus dijaga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 60 yang mengingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Dalam konteks ini, ketahanan pangan yang berkelanjutan berarti mengelola pertanian, perikanan, dan sumber pangan lainnya dengan cara yang ramah lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghindari praktik yang menimbulkan krisis ekologis.
Ketahanan pangan juga memerlukan partisipasi kolektif seluruh lapisan masyarakat. Islam mengajarkan semangat gotong royong melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan kelompok miskin dan rentan. Distribusi kekayaan melalui instrumen sosial ini memastikan bahwa ketersediaan pangan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas dan empati sosial yang menguatkan kohesi umat.
Dalam praktiknya, Rasulullah SAW memberikan teladan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kemandirian pangan. Beliau mendorong umat untuk bekerja, bertani, dan mengelola tanah agar tidak bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Pada masa pemerintahan para khalifah, kebijakan pengelolaan irigasi, pemberian lahan produktif, dan perlindungan terhadap hak-hak petani menjadi bukti bahwa ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam membangun masyarakat yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan panduan normatif, tetapi juga kebijakan praktis yang mendukung tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.
Dari perspektif hadis, ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan konsep keberkahan dan kemandirian, yang keduanya merupakan fondasi penting dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Rasulullah SAW menekankan bahwa makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangan sendiri memiliki nilai lebih, bukan hanya secara material tetapi juga secara spiritual. Dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Bukhari, beliau bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dihasilkan dari usaha tangan sendiri, mengisyaratkan bahwa bekerja dan mengusahakan pangan sendiri adalah bagian dari upaya memperoleh keberkahan hidup. Dengan demikian, ketahanan pangan bukan semata urusan logistik atau ekonomi, tetapi juga ibadah yang mendatangkan ridha Allah ketika dikelola dengan cara yang halal, mandiri, dan penuh tanggung jawab.
Konsep keberkahan dalam hadis ini memberikan pemahaman bahwa pangan yang diperoleh melalui usaha sendiri akan membawa kebaikan yang melimpah, baik dalam bentuk kecukupan, kesehatan, maupun keberlangsungan sumber rezeki tersebut. Keberkahan yang dimaksud bukan hanya kuantitas yang banyak, tetapi kualitas yang memberi manfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya mengejar produktivitas semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, kehalalan, dan keadilan dalam proses pengelolaan pangan. Dengan kata lain, produksi pangan yang dilakukan secara mandiri bukan hanya soal mencukupi kebutuhan jasmani, tetapi juga sarana meraih ketenangan batin karena dikerjakan sesuai tuntunan syariah.
Hadis ini juga menekankan pentingnya kemandirian sebagai strategi fundamental dalam membangun ketahanan pangan. Ketergantungan pada impor atau bantuan luar bukanlah pilihan yang ideal bagi umat, karena hal tersebut dapat melemahkan posisi ekonomi dan kedaulatan suatu bangsa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketahanan pangan yang sejati hanya dapat dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, mengelola lahan produktif, serta memberdayakan tenaga kerja yang ada di dalam masyarakat. Pandangan ini relevan hingga hari ini, di mana kemandirian pangan menjadi salah satu indikator penting kedaulatan negara dan kekuatan ekonomi.
Lebih jauh, Rasulullah SAW memberikan teladan konkret dalam mendorong masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan. Beliau tidak hanya memberikan arahan normatif, tetapi juga menggalakkan praktik nyata dengan mengelola tanah dan mendukung aktivitas bercocok tanam. Dalam sejarah, Rasulullah memotivasi para sahabat untuk memanfaatkan tanah secara produktif, bahkan memberikan lahan kepada mereka yang siap mengelolanya. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tugas kolektif yang harus ditopang oleh sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
Pengelolaan tanah yang digalakkan Rasulullah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan sesaat, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Pengembangan sektor pertanian diarahkan agar masyarakat memiliki kecakapan, teknologi, dan sistem yang mampu menopang ketersediaan pangan jangka panjang. Dalam konteks ini, ketahanan pangan yang Islami tidak hanya berhenti pada kemandirian produksi, tetapi juga meliputi pengelolaan sumber daya secara strategis agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketimpangan distribusi.
Rasulullah juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam membangun ketahanan pangan. Ketika hasil pangan dikelola secara kolektif dan didistribusikan dengan prinsip keadilan, maka manfaatnya akan dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat. Hadis-hadis tentang keutamaan sedekah dan distribusi rezeki yang adil menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada swasembada, tetapi juga pada pemerataan akses bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberkahan dalam pangan juga hadir ketika ia menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menghapus kesenjangan sosial.
Relevansi ajaran Rasulullah tentang kemandirian pangan ini sangat nyata dalam menghadapi tantangan modern seperti ketergantungan impor, krisis pangan global, dan perubahan iklim. Dengan menghidupkan kembali semangat kemandirian yang diajarkan Nabi, umat Islam dapat membangun sistem pangan yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan lebih berkelanjutan. Hal ini melibatkan optimalisasi teknologi, penguatan kapasitas petani, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri. Prinsip-prinsip yang diwariskan Rasulullah menjadi landasan untuk mengembangkan model ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berkeadilan.
Faktualnya, sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa konsep ketahanan pangan bukanlah wacana abstrak, melainkan telah diimplementasikan secara nyata sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa beliau, salah satu kebijakan yang menonjol adalah pendirian pasar Madinah (sūq al-Madīnah) yang bebas dari praktik monopoli. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi barang, termasuk bahan pangan, berjalan adil dan tidak dikuasai segelintir pihak yang berpotensi memanipulasi harga. Dengan mekanisme pasar yang sehat, masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan tanpa hambatan dari praktik spekulasi. Inisiatif ini mencerminkan perhatian Rasulullah terhadap aspek keadilan distribusi sebagai pilar ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak mengalami ketimpangan dalam memperoleh kebutuhan dasar mereka.
Rasulullah SAW juga menekankan prinsip transparansi dan kejujuran dalam perdagangan, termasuk perdagangan pangan. Beliau melarang keras praktik penimbunan (iḥtikār) yang dapat menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga secara tidak wajar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang mengutuk pedagang yang menimbun barang demi keuntungan pribadi. Larangan ini memiliki dampak signifikan dalam menjaga kestabilan pasar, terutama pada masa krisis atau kelangkaan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan pada era Nabi dibangun melalui kombinasi kebijakan pasar yang adil, pengawasan terhadap praktik dagang, dan penegakan nilai-nilai moral dalam kegiatan ekonomi.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, konsep ketahanan pangan berkembang lebih sistematis dengan lahirnya berbagai kebijakan terkait pengelolaan sumber daya pertanian. Umar mengambil langkah strategis dengan mendistribusikan lahan produktif kepada masyarakat yang mampu mengelolanya, sehingga tanah yang terbengkalai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan. Kebijakan ini tidak hanya mengoptimalkan sumber daya yang ada, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, memperkuat basis ekonomi masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Umar memahami bahwa ketersediaan pangan harus ditopang oleh produksi lokal yang kuat, sehingga masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh fluktuasi pasokan dari wilayah lain.
Selain distribusi lahan, Umar bin Khattab juga mengembangkan sistem irigasi secara masif. Jaringan irigasi yang dibangun di berbagai wilayah memungkinkan peningkatan produktivitas pertanian, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya bergantung pada curah hujan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan volume produksi pangan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan pada musim-musim kering. Pengelolaan irigasi ini merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam ketahanan pangan, di mana hasilnya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era kekhalifahan, pembangunan infrastruktur pangan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Langkah-langkah tersebut juga memperlihatkan adanya sinergi antara kebijakan ekonomi dan sosial. Umar tidak hanya memfokuskan pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memastikan distribusinya merata. Beliau mendirikan baitul mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara, termasuk untuk mendanai kebutuhan pangan masyarakat miskin. Dalam kondisi darurat seperti musim paceklik, Umar memerintahkan agar kebutuhan pangan masyarakat ditanggung oleh negara melalui distribusi dari baitul mal. Model ini membuktikan bahwa ketahanan pangan dalam Islam tidak sekadar tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipikul oleh negara.
Perhatian besar Umar terhadap sektor pertanian juga terlihat dari kebijakan perlindungan terhadap petani. Beliau memastikan agar beban pajak pertanian (kharaj) tidak memberatkan, sehingga petani memiliki motivasi untuk terus mengolah tanah mereka. Umar memahami bahwa kesejahteraan petani adalah kunci ketahanan pangan, sebab mereka adalah pihak yang berada di garis terdepan dalam penyediaan bahan pangan. Dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi para petani, produksi pangan dapat terus meningkat dan terjaga kestabilannya.
Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi potensi krisis pangan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tanggap terhadap masalah kelaparan, seperti yang terjadi pada masa paceklik (ām al-ramādah). Dalam kondisi tersebut, beliau mengambil langkah cepat dengan mengimpor pangan dari daerah lain, mengatur distribusinya, dan menanggung biaya hidup masyarakat miskin hingga keadaan kembali normal. Penanganan krisis ini menunjukkan bagaimana ketahanan pangan dalam Islam tidak hanya mengandalkan kebijakan jangka panjang, tetapi juga kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
Selain itu, Islam memandang ketahanan pangan sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial yang harus dipikul bersama oleh individu, masyarakat, dan negara. Pangan dalam Islam tidak semata-mata diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi secara adil bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, Islam menghadirkan berbagai instrumen distribusi kekayaan seperti zakat pertanian, infak, dan sedekah untuk menjamin agar kebutuhan pangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Instrumen-instrumen ini bukan sekadar amal kebajikan, tetapi bagian dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan distribusi.
Konsep zakat pertanian, misalnya, memiliki dimensi yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Zakat ini diwajibkan atas hasil panen dengan kadar tertentu, yang kemudian disalurkan kepada kelompok mustahik, seperti fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Mekanisme ini memastikan bahwa hasil pertanian tidak hanya dinikmati oleh pemilik lahan, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap pangan. Hal ini memperlihatkan bagaimana Islam menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan zakat, distribusi pangan menjadi lebih merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah timbulnya ketidakstabilan akibat kelaparan.
Infak dan sedekah melengkapi peran zakat dalam sistem distribusi pangan. Keduanya bersifat sukarela tetapi sangat dianjurkan, bahkan ditekankan sebagai bentuk solidaritas sosial yang memperkuat ikatan antarumat. Melalui infak dan sedekah, kelebihan pangan dan kekayaan yang dimiliki oleh individu mampu menjadi solusi konkret bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa memberi makan orang yang lapar termasuk amalan yang sangat mulia, karena secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan adanya budaya berbagi ini, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi kewajiban moral setiap individu Muslim.
Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ayat ini menjadi landasan kuat bagi distribusi sumber daya yang lebih merata, termasuk dalam konteks pangan. Islam menolak sistem ekonomi yang membuat akses terhadap pangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara yang lain terpinggirkan. Sebaliknya, Islam mendorong sirkulasi kekayaan yang inklusif, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan dapat terpenuhi secara adil. Prinsip ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dalam Islam memiliki dimensi keadilan sosial yang mendalam, di mana kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama.
Sejarah peradaban Islam memberikan bukti nyata bagaimana penerapan zakat dan instrumen sosial lainnya mampu menciptakan ketahanan pangan yang kuat. Pada masa Khilafah, zakat dikelola dengan baik oleh baitul mal sehingga distribusinya berjalan efektif. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat yang dikumpulkan begitu melimpah hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dikelola sesuai prinsip Islam tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, ketahanan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan sistem ekonomi Islam.
Selain menjamin distribusi pangan, mekanisme zakat, infak, dan sedekah juga berperan sebagai instrumen pencegahan krisis sosial. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan terpenuhi, potensi konflik sosial akibat kesenjangan dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik suatu masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara merata, umat dapat hidup dalam harmoni, yang pada akhirnya memperkuat struktur sosial dan solidaritas antarwarga.
Dalam konteks modern, prinsip distribusi yang diajarkan Islam tetap relevan sebagai solusi menghadapi ketimpangan akses pangan yang masih terjadi di banyak negara. Dengan menghidupkan kembali peran zakat pertanian, infak, dan sedekah secara optimal, umat Islam dapat membangun sistem ketahanan pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Integrasi instrumen sosial Islam ke dalam kebijakan pangan nasional juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi krisis pangan global. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang distribusi pangan tidak hanya bernilai historis, tetapi juga aplikatif untuk menjawab tantangan kontemporer.
Dalam konteks kontemporer, perspektif Al-Qur’an dan hadis tentang ketahanan pangan tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pijakan membangun sistem pangan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang diajarkan Islam mengenai pengelolaan sumber daya, distribusi yang adil, dan etika konsumsi menjadi panduan penting dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Ketahanan pangan saat ini bukan sekadar soal ketersediaan bahan pangan, melainkan juga menyangkut pemerataan akses, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Al-Qur’an telah memberikan pedoman untuk memanfaatkan rezeki Allah dengan cara yang baik, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kerusakan, sehingga membangun ketahanan pangan menjadi bagian dari amanah umat manusia sebagai khalifah di bumi.
Tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, membawa dampak langsung pada produksi pangan. Bencana alam, cuaca ekstrem, dan degradasi lahan menurunkan produktivitas pertanian serta mengganggu distribusi pangan global. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam mengajarkan perlunya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pertanian berkelanjutan, pemeliharaan ekosistem, dan pengurangan praktik yang merusak lingkungan sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perusakan bumi. Ketahanan pangan yang Islami harus mengedepankan kelestarian sumber daya, sehingga generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menuntut sistem pangan yang lebih efektif dan berdaya tahan. Islam menawarkan konsep efisiensi dan produktivitas yang berimbang dengan prinsip keadilan sosial. Peningkatan kapasitas produksi pangan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat kecil atau memperlebar kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, Islam menuntut agar setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pangan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran zakat dan sedekah yang mendistribusikan kelebihan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai ini, ketahanan pangan dapat diupayakan secara inklusif, sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketimpangan akses terhadap pangan yang terjadi di banyak negara menuntut penegakan keadilan distribusi sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur’an. Surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, yang dalam konteks modern berarti pangan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Ketahanan pangan membutuhkan mekanisme yang memungkinkan setiap orang, tanpa memandang status sosial, dapat menikmati akses yang setara terhadap kebutuhan pokok mereka. Dengan demikian, sistem pangan yang Islami tidak hanya menekankan pada produksi, tetapi juga pada distribusi yang merata.
Pendekatan berbasis syariah ini menuntut adanya kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung produksi pangan berkelanjutan, pengendalian harga, dan perlindungan terhadap petani kecil. Sektor swasta diharapkan dapat berinovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, sedangkan masyarakat berperan menjaga pola konsumsi yang moderat dan mendukung produk lokal. Kolaborasi ini akan membentuk sistem pangan yang kokoh, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
Selain itu, etika konsumsi yang diajarkan Islam harus dihidupkan kembali dalam konteks modern. Konsumsi berlebihan, pemborosan pangan, dan gaya hidup yang tidak ramah lingkungan menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Surah Al-A‘raf ayat 31 mengingatkan agar manusia makan dan minum tetapi tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dengan menerapkan pola konsumsi yang moderat, masyarakat dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem pangan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pangan juga membuka peluang besar untuk mengembangkan produk halal dan thayyib yang menjadi keunggulan kompetitif di pasar global. Dengan memadukan keberlanjutan, kehalalan, dan keadilan dalam satu sistem, Indonesia khususnya dapat membangun posisi strategis dalam rantai pasok pangan dunia. Prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat menjawab kebutuhan zaman sekaligus memperkuat daya saing umat di tingkat internasional.
Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Islam adalah konsep holistik yang menggabungkan aspek teologis, etis, sosial, dan ekonomi. Perspektif Al-Qur’an dan hadis memberikan arahan yang jelas bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan material, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab kolektif umat manusia. Islam mengajarkan bahwa upaya menjaga ketersediaan dan distribusi pangan yang adil adalah bentuk pengamalan iman, yang pada akhirnya akan membawa pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.