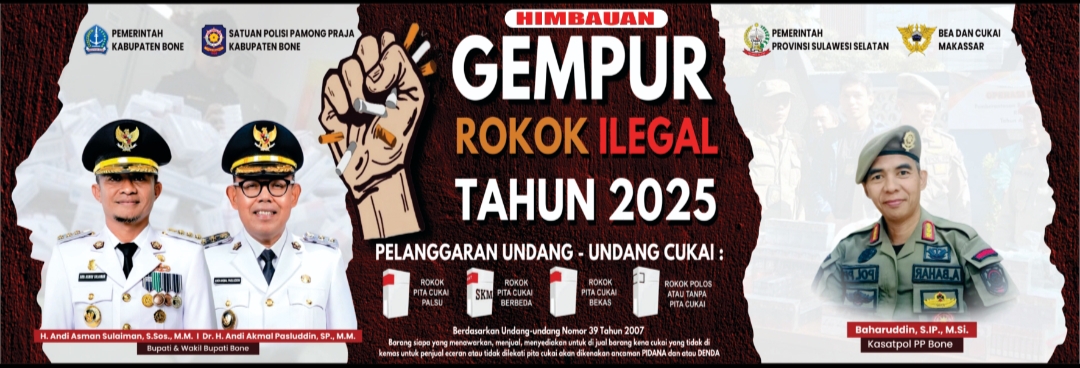Oleh: Prof. Syaparuddin, Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
KETAHANAN pangan merupakan salah satu isu krusial yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan bangsa. Dalam perspektif Islam, ketahanan pangan tidak cukup hanya dipahami sebagai ketersediaan bahan pangan, melainkan juga sebagai kedaulatan umat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkeadilan. Konsep food sovereignty yang digaungkan secara global sejatinya sudah lama terinternalisasi dalam ajaran Islam, yakni ketika umat didorong untuk menguasai produksi pangan sendiri, tidak bergantung secara berlebihan pada impor, serta memastikan distribusinya merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kedaulatan pangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor beras, gandum, kedelai, gula, dan berbagai bahan pangan pokok lainnya menjadikan masyarakat Muslim sangat rentan terhadap guncangan harga global maupun gangguan pasokan internasional. Krisis pangan dunia yang dipicu oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, atau kebijakan proteksionis negara eksportir sering kali langsung berdampak pada stabilitas pangan di dalam negeri. Ketidakstabilan ini bukan hanya mengancam kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial dan melemahkan ketahanan ekonomi nasional.
Dalam konteks Indonesia, ketergantungan pada impor pangan seakan menjadi paradoks mengingat negeri ini dikenal sebagai negara agraris dengan lahan subur dan kekayaan alam yang melimpah. Potensi yang besar sering kali belum dikelola secara optimal karena keterbatasan infrastruktur pertanian, lemahnya permodalan petani kecil, dan sistem distribusi yang belum efisien. Akibatnya, petani Muslim yang sebenarnya berada di garis depan produksi pangan justru sering terpinggirkan. Padahal, jika diberdayakan dengan serius, komunitas petani Muslim dapat menjadi kekuatan strategis dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Islam memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pusat penguatan umat. Dalam maqāṣid al-sharī‘ah, menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) menjadi tujuan utama yang hanya dapat dicapai bila pangan tersedia dengan cukup, terjangkau, dan dikelola dengan adil. Petani yang diberdayakan bukan hanya menghasilkan bahan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan upaya kolektif menjaga kehidupan. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual yang menegaskan pentingnya kedaulatan pangan dalam kerangka syariah.
Tantangan kedaulatan pangan di negara Muslim juga terkait dengan struktur ekonomi global yang tidak berpihak kepada petani kecil. Pasar pangan dunia didominasi oleh korporasi multinasional yang menguasai perdagangan benih, pupuk, dan distribusi pangan. Ketika petani Muslim masih bergantung pada input pertanian impor, posisi tawar mereka melemah, dan produktivitas pun sulit berkembang. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas petani Muslim harus diarahkan pada penguatan kemandirian, mulai dari penyediaan benih lokal unggul, pengolahan pupuk organik, hingga pembangunan rantai pasok berbasis komunitas.
Selain itu, masalah ketidakadilan distribusi dan lemahnya akses pasar juga menjadi penghambat besar bagi petani Muslim. Banyak hasil pertanian yang dijual dengan harga murah di tingkat petani, tetapi dijual mahal di tingkat konsumen karena dikuasai oleh tengkulak dan jaringan distribusi yang tidak adil. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem ekonomi syariah yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama. Dengan memperkuat koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan model kemitraan Islami, petani dapat memperoleh akses permodalan dan distribusi yang lebih adil sehingga hasil pertanian benar-benar memberikan kesejahteraan bagi mereka.
Perubahan iklim juga menambah kompleksitas masalah kedaulatan pangan di negara Muslim. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan berpengaruh besar terhadap produktivitas pertanian. Dalam menghadapi kondisi ini, pemberdayaan petani Muslim harus disertai dengan inovasi teknologi yang ramah lingkungan serta penguatan kesadaran ekologis yang sejalan dengan ajaran Islam tentang amanah menjaga bumi. Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Maka, strategi pertanian berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan pangan di masa depan.
Lebih jauh, pemberdayaan petani Muslim juga harus dipandang sebagai strategi politik untuk memperkuat kemandirian bangsa. Negara yang bergantung pada impor pangan akan mudah terpengaruh oleh tekanan dan kepentingan negara lain. Sebaliknya, negara yang berdaulat atas pangannya akan lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politiknya. Dalam perspektif Islam, kemandirian ini adalah bagian dari menjaga martabat umat agar tidak menjadi lemah di hadapan dominasi pihak luar. Dengan demikian, kedaulatan pangan harus dipahami bukan hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ketahanan nasional dan perlawanan terhadap hegemoni global.
Pemberdayaan petani Muslim dalam konteks kedaulatan pangan tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai pemberian bantuan modal semata. Bantuan finansial memang penting, namun jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi, maka hasilnya hanya akan bersifat sementara. Islam menekankan pentingnya transformasi menyeluruh yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diarahkan pada penguatan kemampuan petani untuk mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan dalam sistem pangan.
Aspek pendidikan menjadi titik krusial dalam pemberdayaan petani Muslim. Literasi pertanian modern, manajemen usaha tani, serta pemahaman tentang pasar menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan global. Lebih dari itu, literasi finansial syariah sangat penting agar petani tidak terjerat praktik riba yang membebani dan merugikan. Dengan memahami prinsip-prinsip muamalah Islam, petani dapat mengelola modal, keuntungan, dan risiko usaha dengan cara yang halal dan lebih menenteramkan. Pendidikan semacam ini bukan hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga membangun kesadaran bahwa bertani adalah amanah sekaligus ladang ibadah.
Dari sisi kelembagaan, keberadaan organisasi berbasis syariah menjadi penopang utama kemandirian petani. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan koperasi syariah hadir sebagai solusi alternatif untuk menyediakan akses permodalan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Melalui lembaga-lembaga ini, petani dapat memperoleh pembiayaan tanpa riba, berbasis bagi hasil, serta mendapat dukungan dalam pengelolaan usaha tani secara kolektif. Kelembagaan ini sekaligus memperkuat solidaritas antarpetani, sehingga mereka tidak berjalan sendiri, tetapi bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menopang dan saling memberdayakan.
Penggunaan teknologi pertanian modern juga menjadi bagian integral dari pemberdayaan petani Muslim. Teknologi seperti sistem irigasi pintar, bibit unggul lokal, pupuk organik, hingga digitalisasi pemasaran dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap disinergikan dengan nilai-nilai Islam, yakni tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan eksploitasi, dan tetap menjaga keberlanjutan. Dengan cara ini, pertanian modern tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang merupakan amanah dari Allah SWT.
Akses pasar yang lebih luas juga menentukan keberhasilan pemberdayaan. Selama ini, petani Muslim kerap terjebak dalam rantai distribusi panjang yang tidak adil, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak atau perantara. Dengan memanfaatkan jaringan koperasi, marketplace syariah, maupun platform digital, petani dapat menjual produknya langsung ke konsumen dengan harga yang lebih layak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menolak monopoli dan menekankan keadilan dalam perdagangan. Dengan akses pasar yang baik, kesejahteraan petani dapat meningkat secara signifikan.
Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani Muslim juga tidak bisa diabaikan. Kebijakan pertanian yang berpihak, regulasi yang adil, serta program pendampingan berbasis syariah perlu diimplementasikan agar petani memiliki ekosistem yang kondusif. Pemerintah dapat menjadi fasilitator yang mempertemukan petani dengan lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan ini penting agar pemberdayaan tidak hanya menjadi inisiatif komunitas, tetapi juga bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Lebih jauh, pemberdayaan petani Muslim harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan sinergi. Pendidikan, kelembagaan, teknologi, pasar, dan kebijakan harus berjalan beriringan agar mampu membangun ketahanan pangan dari akar rumput. Jika salah satu aspek ini diabaikan, maka pemberdayaan tidak akan menghasilkan transformasi yang nyata. Sinergi antara ulama, akademisi, praktisi pertanian, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam membentuk kerangka pemberdayaan yang utuh.
Kedaulatan pangan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari prinsip pemanfaatan potensi lokal dan kearifan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan, sehingga praktik pertanian lokal yang ramah alam sejalan dengan nilai-nilai istidāmah atau keberlanjutan. Dalam banyak komunitas Muslim, praktik bercocok tanamtradisional yang memanfaatkan kearifan lokal terbukti mampu menjaga ketahanan pangan keluarga dan komunitas, sekaligus memperkuat identitas budaya yang melekat pada sistem pangan daerah.
Diversifikasi pangan berbasis tanaman lokal menjadi salah satu strategi penting yang harus dikedepankan. Ketergantungan pada satu atau dua jenis tanaman pokok, seperti beras atau gandum, membuat masyarakat rentan terhadap krisis pangan ketika terjadi gangguan pasokan. Padahal, Indonesia dan negara Muslim lain memiliki kekayaan tanaman lokal seperti sagu, jagung, umbi-umbian, hingga kacang-kacangan yang memiliki nilai gizi tinggi. Islam mendorong umat untuk memanfaatkan aneka rezeki yang Allah sediakan di bumi, sehingga diversifikasi pangan bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga wujud syukur atas karunia alam yang melimpah.
Penggunaan bibit unggul yang sesuai dengan ekosistem daerah juga sangat relevan dengan prinsip Islam tentang kesesuaian (munāsabah) dan keseimbangan (tawāzun). Bibit lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi tanah, iklim, dan ekosistem tertentu biasanya lebih tahan terhadap penyakit, lebih hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan. Dengan memberdayakan petani untuk mengembangkan dan melestarikan benih lokal, kedaulatan pangan akan semakin kokoh, sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih impor yang kerap dikendalikan oleh perusahaan multinasional dengan sistem monopoli.
Sistem irigasi berbasis komunitas juga merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang sejalan dengan nilai Islam. Dalam sejarah Islam, praktik pengelolaan air secara kolektif sudah lama dilakukan, misalnya melalui sistem hisbah yang mengatur distribusi air untuk kepentingan masyarakat. Irigasi komunitas memungkinkan pemanfaatan sumber daya air secara adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan bahwa setiap petani, termasuk yang kecil sekalipun, tetap mendapat hak yang sama dalam mengakses air sebagai sumber kehidupan.
Ketergantungan pada pupuk dan benih impor yang sering dikendalikan korporasi multinasional menciptakan jebakan ketidakmandirian yang berbahaya bagi petani Muslim. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan ekonomi yang menimbulkan ketergantungan dan eksploitasi. Karena itu, membangun kemandirian melalui pemanfaatan pupuk organik, teknologi lokal, dan bibit hasil inovasi komunitas menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang hakiki. Semangat ini sesuai dengan pesan Al-Qur’an agar umat tidak menyerahkan masa depannya kepada pihak luar yang bisa merugikan mereka.
Lebih jauh, pemanfaatan potensi lokal juga memperkuat basis ekonomi masyarakat desa yang menjadi pusat kehidupan petani Muslim. Produk pangan lokal dapat diolah menjadi komoditas bernilai tambah, dipasarkan secara luas, bahkan menjadi identitas khas daerah yang mendukung pariwisata halal dan ekonomi kreatif berbasis syariah. Dengan begitu, kedaulatan pangan tidak hanya berbicara tentang kecukupan konsumsi, tetapi juga tentang penciptaan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semangat kemandirian yang ditanamkan Islam harus terus dihidupkan agar umat mampu bertahan menghadapi dinamika global. Krisis pangan, perubahan iklim, maupun fluktuasi pasar internasional adalah tantangan nyata yang membutuhkan ketahanan internal. Ketika umat Islam memiliki basis produksi pangan yang mandiri, diversifikasi yang kuat, serta dukungan kearifan lokal, maka mereka tidak akan mudah goyah oleh tekanan eksternal. Kemandirian ini adalah bentuk nyata dari prinsip izzah (kemuliaan) umat, yaitu tidak menjadi lemah dan bergantung pada pihak lain.
Di samping aspek ekonomi, pemberdayaan petani Muslim memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam dan khas dalam tradisi Islam. Aktivitas bertani tidak semata-mata dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup atau mencari keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Islam menempatkan kerja di bidang pertanian sebagai bagian dari amal shalih yang bernilai ibadah. Dengan niat yang benar, bercocok tanam menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hasil dari aktivitas itu memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta.
Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap tanaman yang ditanam lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, akan dicatat sebagai sedekah bagi penanamnya. Hadis ini memberikan perspektif yang sangat luas bahwa manfaat pertanian melampaui batas kepentingan pribadi. Bahkan ketika hasil panen tidak sepenuhnya dinikmati oleh manusia, ia tetap bernilai ibadah karena menjadi rezeki bagi makhluk Allah lainnya. Dengan demikian, petani Muslim memiliki motivasi spiritual yang lebih kuat dalam bekerja, sebab setiap benih yang mereka tanam sesungguhnya adalah ladang pahala yang berkelanjutan.
Spiritualitas ini juga menjadi modal sosial yang penting dalam membangun komunitas pertanian Muslim yang kokoh. Ketika bertani dianggap sebagai ibadah, maka etos kerja, kejujuran, dan kepedulian sosial akan lebih mudah tumbuh dalam praktik pertanian. Petani yang menyadari dimensi ibadah dalam pekerjaannya tidak akan mudah melakukan kecurangan, merusak lingkungan, atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Sebaliknya, mereka akan menjaga kelestarian tanah, air, dan udara sebagai bentuk amanah yang harus dipelihara. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam.
Lebih dari itu, dimensi spiritual dalam pemberdayaan petani Muslim juga menumbuhkan semangat keberlanjutan. Kesadaran bahwa bertani adalah ibadah menjadikan mereka lebih tekun dalam merawat tanaman, lebih sabar menghadapi risiko gagal panen, dan lebih optimis dalam menghadapi tantangan pertanian. Mereka tidak sekadar menanam untuk satu musim, tetapi juga memikirkan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Kesabaran dan ketekunan yang dilandasi iman inilah yang menjadi kekuatan moral untuk menjaga kesinambungan pertanian dalam jangka panjang.
Kesadaran religius ini juga memperkuat kepedulian sosial dalam komunitas petani. Islam mendorong agar rezeki yang diperoleh dari hasil bumi tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat pertanian, sedekah hasil panen, dan tradisi berbagi pangan dalam masyarakat Muslim adalah manifestasi nyata dari integrasi aspek spiritual dengan ekonomi. Dengan begitu, pertanian tidak hanya menghasilkan bahan makanan, tetapi juga mempererat ikatan sosial, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat jaringan kepedulian antaranggota masyarakat.
Pemberdayaan petani Muslim yang menekankan aspek spiritual ini juga berimplikasi pada kualitas hasil pertanian. Petani yang bekerja dengan niat ibadah akan menjaga kehalalan dan kebaikan (halalan thayyiban) dari produk yang dihasilkan. Mereka akan menghindari praktik yang merugikan konsumen, seperti penggunaan bahan kimia berlebihan atau manipulasi dalam distribusi. Hal ini bukan hanya meningkatkan daya saing produk Muslim di pasar, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keberkahan bagi masyarakat yang mengonsumsinya.
Dengan menjadikan pertanian sebagai ibadah, umat Islam dapat membangun sistem pangan yang lebih beretika, berkeadilan, dan berkeberlanjutan. Petani Muslim tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keberlangsungan hidup umat dan makhluk lain. Mereka mengemban tanggung jawab ganda: memenuhi kebutuhan jasmani masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai spiritual yang diwariskan Islam. Hal ini menjadikan posisi petani Muslim sangat mulia, karena kerja keras mereka berkontribusi langsung pada kemaslahatan umat.
Dengan demikian, kedaulatan pangan dan pemberdayaan komunitas petani Muslim tidak bisa sekadar dipandang sebagai agenda ekonomi yang terbatas pada peningkatan produksi dan distribusi. Lebih dari itu, ia adalah agenda peradaban yang menyangkut martabat, identitas, dan keberlangsungan hidup umat. Sebuah bangsa yang berdaulat atas pangannya akan terhindar dari ketergantungan pada pihak luar, sehingga lebih mampu menentukan arah pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyatnya sendiri. Islam mengajarkan bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari menjaga kemuliaan umat (izzah al-ummah), karena hanya dengan penguasaan pangan umat dapat berdiri tegak menghadapi tantangan global.
Kedaulatan pangan juga membawa implikasi besar bagi stabilitas politik suatu negara. Bangsa yang bergantung pada impor pangan rentan terhadap tekanan diplomatik dan intervensi ekonomi dari negara produsen. Sebaliknya, bangsa yang mampu mengelola pangan secara mandiri memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pergaulan internasional. Dalam kerangka Islam, hal ini merupakan manifestasi dari prinsip ḥifẓ al-dawlah (menjaga kedaulatan negara), yang menegaskan bahwa kekuatan politik tidak bisa dilepaskan dari kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan petani Muslim adalah investasi strategis dalam memperkuat fondasi politik bangsa.
Dari sisi sosial, kedaulatan pangan berperan penting dalam menciptakan stabilitas masyarakat. Ketika pangan tersedia secara cukup, terjangkau, dan merata, potensi konflik sosial akibat kelangkaan atau disparitas harga dapat diminimalisir. Sebaliknya, krisis pangan sering kali menjadi pemicu kerusuhan, ketidakpuasan, bahkan ketidakstabilan pemerintahan. Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat agar tidak ada pihak yang tertinggal. Dengan memberdayakan petani Muslim, distribusi pangan dapat lebih terkendali karena produksi dilakukan oleh komunitas yang dekat dengan masyarakat, bukan semata-mata oleh korporasi besar yang berorientasi profit.
Kedaulatan pangan juga berdampak pada kekuatan budaya. Pertanian lokal yang berbasis kearifan tradisional tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga melahirkan identitas kuliner, tradisi sosial, dan nilai-nilai kebersamaan yang memperkuat jati diri bangsa. Dengan melestarikan pangan lokal, umat Muslim dapat menjaga warisan budaya sekaligus membangun daya saing di tingkat global melalui produk-produk khas daerah. Islam mendorong umatnya untuk bangga pada potensi lokal, karena keberagaman pangan adalah bagian dari nikmat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemberdayaan petani Muslim menjadi benteng budaya sekaligus fondasi ekonomi yang berkelanjutan.
Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dan kekayaan agraris yang besar memiliki peluang emas untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbasis nilai syariah. Potensi lahan yang luas, keanekaragaman hayati, serta jumlah petani Muslim yang besar merupakan modal utama untuk membangun sistem pangan yang mandiri. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan bila dikelola dengan visi peradaban, bukan sekadar kepentingan jangka pendek. Islam memberikan kerangka moral yang jelas: pertanian harus berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan, sehingga hasilnya bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan.
Untuk mencapai tujuan besar tersebut, dibutuhkan sinergi antarberbagai pihak. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang berpihak pada petani kecil, ulama perlu memberikan bimbingan moral dan etika dalam praktik pertanian, akademisi dapat menyumbangkan inovasi teknologi dan penelitian, sementara sektor swasta berperan dalam memperluas akses pasar dan rantai distribusi. Masyarakat luas juga harus mendukung dengan memilih produk lokal dan menghargai kerja keras petani. Sinergi ini menciptakan ekosistem pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.
Ekosistem pertanian berbasis syariah yang berkelanjutan berarti mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka utuh. Produksi pertanian tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian alam dan kesejahteraan sosial. Sistem pembiayaan syariah, distribusi adil, dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan harus menjadi pilar utama. Dengan demikian, pertanian dapat berkembang tanpa menimbulkan ketimpangan atau kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang menekankan keseimbangan (mīzān) dalam setiap aspek kehidupan.
Akhirnya, memperjuangkan kedaulatan pangan adalah bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang kuat, adil, dan mandiri. Pemberdayaan petani Muslim adalah kunci untuk mencapainya, karena mereka bukan hanya penghasil pangan, tetapi juga penopang kemandirian bangsa. Saatnya umat meneguhkan tekad bahwa pangan tidak boleh lagi menjadi alat ketergantungan, melainkan simbol kedaulatan dan keberkahan. Dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Islam, kedaulatan pangan dapat diwujudkan demi kesejahteraan umat dan kejayaan bangsa.