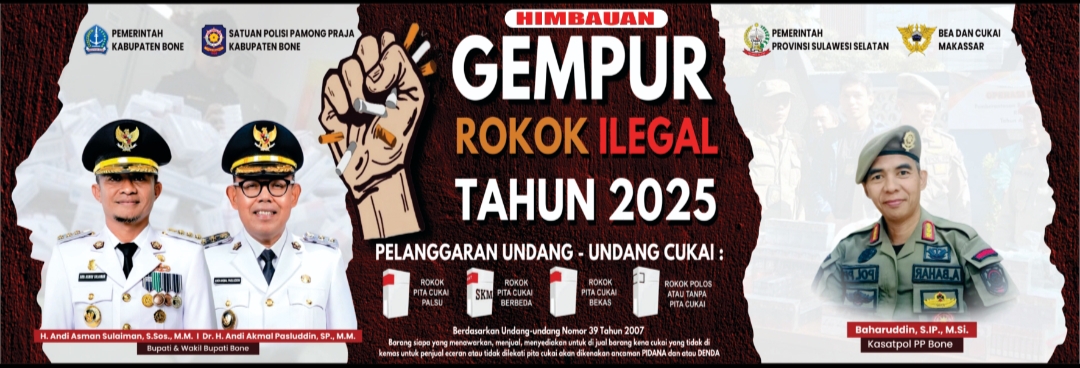Oleh: Prof. Syaparuddin, Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
KETAHANAN pangan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang luas, terutama ketika dihadapkan pada krisis pangan global yang kini semakin nyata. Secara konseptual, Islam menempatkan pangan bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi sebagai amanah ilahi yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Al-Qur’an menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan (mīzān) dan larangan terhadap pemborosan (isrāf) dalam konsumsi, karena keduanya menjadi akar dari ketimpangan dan kerusakan ekologis. Dengan demikian, krisis pangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi atau logistik semata, melainkan sebagai refleksi dari lemahnya kesadaran moral manusia terhadap tanggung jawabnya kepada Allah, alam, dan sesama.
Secara faktual, krisis pangan global telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi dunia. Kenaikan harga komoditas pangan utama seperti gandum, beras, dan jagung menyebabkan jutaan orang di berbagai belahan dunia kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inflasi pangan menekan daya beli masyarakat miskin dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Di banyak negara berkembang, ketergantungan pada impor pangan semakin memperparah situasi ketika rantai pasok global terganggu akibat konflik atau kebijakan proteksionis negara produsen. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan hanya masalah ketersediaan, tetapi juga persoalan keadilan distribusi dan tata kelola global yang timpang.
Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk krisis pangan. Pergeseran pola cuaca, kekeringan ekstrem, banjir, dan peningkatan suhu global mengakibatkan penurunan produktivitas lahan pertanian di berbagai wilayah. Petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan dunia paling merasakan dampaknya. Mereka kehilangan hasil panen, pendapatan, dan bahkan lahan akibat degradasi lingkungan. Dalam pandangan Islam, situasi ini mencerminkan lemahnya kesadaran manusia terhadap amanah Allah untuk menjaga bumi sebagai sumber kehidupan. Kerusakan ekosistem akibat keserakahan manusia bertentangan dengan prinsip keseimbangan (mīzān) yang menjadi fondasi keberlanjutan alam semesta.
Konflik geopolitik seperti perang di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika juga memperburuk ketahanan pangan global. Perang mengganggu distribusi pangan, menghancurkan infrastruktur pertanian, dan mengalihkan anggaran publik dari kesejahteraan rakyat menuju belanja militer. Dalam konteks ajaran Islam, hal ini menegaskan pentingnya perdamaian sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan kemakmuran. Islam memandang bahwa konflik bersenjata yang menimbulkan kelaparan massal merupakan bentuk kezaliman besar terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk berperan aktif dalam diplomasi kemanusiaan dan pembangunan perdamaian sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Islam menawarkan pendekatan yang bersifat komprehensif melalui nilai keadilan sosial (al-‘adālah al-ijtimā‘iyyah) dan solidaritas kemanusiaan (ukhuwwah insāniyyah). Prinsip ini menuntut agar kesejahteraan dan akses terhadap pangan tidak dimonopoli oleh segelintir pihak. Zakat, infak, dan wakaf bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Zakat pertanian, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dengan cara membantu petani kecil memperoleh modal, benih unggul, dan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, ajaran Islam tidak berhenti pada seruan moral, tetapi hadir dengan solusi praktis dan berkelanjutan.
Wakaf produktif menjadi instrumen sosial-ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendukung sistem pangan berkeadilan. Dalam sejarah Islam, banyak lahan pertanian dan perkebunan dikelola sebagai wakaf, hasilnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan bagi fakir miskin. Model ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan aset ekonomi secara kolektif demi kemaslahatan bersama (maṣlaḥah ‘āmmah). Di era modern, konsep wakaf dapat diperluas melalui pengelolaan korporasi berbasis syariah di sektor agrikultur, pengembangan logistik halal, dan pembentukan lembaga pangan wakaf internasional yang berkolaborasi lintas negara Muslim.
Selain mekanisme sosial, Islam juga mendorong inovasi dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari solusi atas krisis pangan. Al-Qur’an berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Inovasi dalam bidang pertanian berkelanjutan, bioteknologi halal, dan efisiensi rantai pasok merupakan wujud aktualisasi nilai ‘ilm (pengetahuan) dalam memecahkan persoalan kemanusiaan. Negara-negara Muslim memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi pangan yang berbasis etika Islam—yakni teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial.
Solidaritas lintas negara Muslim menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Ketika satu negara menghadapi kelaparan, negara lain yang memiliki surplus pangan seharusnya tampil membantu sebagai wujud nyata dari ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Melalui organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), negara-negara Muslim dapat memperkuat kerja sama dalam bidang riset pangan, bantuan kemanusiaan, dan perdagangan adil. Sinergi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dunia Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas global.
Keterlibatan umat Islam dalam menghadapi krisis pangan global sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kesadaran ekologis yang bersumber dari nilai-nilai keislaman. Islam menegaskan bahwa alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga keseimbangannya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam Al-Qur’an, manusia disebut sebagai khalīfah fi al-arḍ, yaitu pemakmur bumi yang bertanggung jawab menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap tindakan dalam produksi dan konsumsi pangan semestinya mencerminkan rasa tanggung jawab ekologis (mas’ūliyyah bi al-bī’ah) yang menolak praktik eksploitasi berlebihan dan menegakkan prinsip keberlanjutan (istidrāmiyyah).
Pandangan Islam terhadap bumi sebagai amanah (amānah) mengandung makna spiritual yang mendalam. Amanah bukan sekadar kepercayaan pasif, tetapi tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa bumi tetap produktif dan lestari bagi generasi mendatang. Ketika manusia merusak tanah pertanian, menebang hutan tanpa reboisasi, atau mencemari air dan udara, sesungguhnya ia telah mengkhianati amanah yang Allah titipkan. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga moral dan sosial, karena merampas hak generasi masa depan untuk menikmati sumber daya yang sama. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab iman (mas’ūliyyah īmāniyyah) dan bukan semata-mata urusan teknis.
Krisis pangan global memperlihatkan dengan jelas hubungan antara kerusakan lingkungan dan kesulitan produksi pangan. Deforestasi yang masif mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya kemampuan alam menyerap karbon, sementara pencemaran tanah dan air menyebabkan penurunan kualitas hasil pertanian. Fenomena ini sejalan dengan peringatan Al-Qur’an dalam Surah ar-Rūm ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga ekologis, menegaskan bahwa krisis ekologis dan krisis pangan adalah dua sisi dari mata uang yang sama—yakni akibat dari perilaku manusia yang abai terhadap keseimbangan dan etika lingkungan.
Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Islam mendorong lahirnya praktik pertanian berkelanjutan yang selaras dengan prinsip halal-thayyib. Pertanian berkelanjutan dalam konteks Islam bukan hanya berarti ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan sosial dan menjamin kesejahteraan petani. Penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan sistem irigasi hemat air adalah wujud nyata dari upaya mengembalikan harmoni alam. Rasulullah SAW bahkan mencontohkan nilai ekologis dalam sabdanya bahwa menanam pohon yang menghasilkan manfaat bagi manusia atau hewan akan dihitung sebagai sedekah. Dengan demikian, aktivitas pertanian bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga amal kebajikan yang bernilai ibadah.
Konservasi air menjadi aspek penting dalam mitigasi krisis pangan. Dalam ajaran Islam, air digambarkan sebagai sumber kehidupan yang suci dan harus digunakan secara bijak. Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk tidak boros menggunakan air bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir deras. Pesan ini mengandung makna ekologis yang kuat, yaitu bahwa setiap tetes air memiliki nilai keberkahan dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui sistem pengairan presisi, penampungan air hujan, dan penggunaan kembali air limbah yang telah diolah untuk mendukung pertanian produktif dan berkelanjutan.
Pemanfaatan energi bersih juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab ekologis umat Islam dalam sistem pangan global. Ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak hanya mempercepat perubahan iklim, tetapi juga menciptakan ketimpangan akses terhadap energi. Islam mendorong inovasi yang membawa kemaslahatan bagi banyak pihak (jalb al-maṣlaḥah) dan menolak kerusakan (daf‘ al-mafsadah). Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan bioenergi halal dalam rantai pasok pangan adalah langkah nyata menuju kemandirian energi dan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.Kesadaran ekologis dalam Islam juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat. Upaya mitigasi krisis pangan tidak bisa dilakukan secara terpisah; ia memerlukan sinergi kebijakan publik, edukasi lingkungan, dan reformasi konsumsi. Masjid, pesantren, dan universitas Islam dapat menjadi pusat pembelajaran ekoteologis yang menanamkan nilai cinta lingkungan sebagai bagian dari akhlak mulia. Dengan menanamkan prinsip bahwa “mencintai bumi berarti mencintai ciptaan Allah,” umat Islam akan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem.
Islam menempatkan kemandirian pangan sebagai bagian penting dari ketahanan umat dan kedaulatan ekonomi. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa rezeki harus diusahakan secara mandiri, bukan bergantung pada pihak lain. Dalam banyak ayat Al-Qur’an, Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia-Nya melalui kerja keras dan inovasi. Oleh karena itu, kemandirian pangan bukan hanya upaya ekonomi, tetapi juga bentuk pengamalan spiritual yang menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab atas nikmat Allah. Umat yang mandiri dalam pangan akan lebih berdaya menghadapi tantangan global, sekaligus lebih mampu menjaga stabilitas sosial dan moralnya.
Nabi Muhammad SAW memberikan teladan nyata tentang pentingnya kerja keras dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beliau terlibat langsung dalam perdagangan dan mendorong para sahabat untuk bekerja, bercocok tanam, dan berdagang dengan cara yang halal. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil jerih payah tangan sendiri. Nilai ini mengajarkan bahwa kemandirian ekonomi adalah bentuk kehormatan diri dan perwujudan iman. Dalam konteks pangan, bekerja di sektor pertanian dan produksi pangan bukan sekadar profesi rendah, melainkan amal yang mulia karena berperan menjaga kehidupan banyak orang.
Dalam konteks modern, kemandirian pangan berarti kemampuan suatu negara atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan pangannya tanpa ketergantungan berlebihan pada impor. Ketergantungan terhadap impor pangan yang tinggi menjadikan suatu bangsa rentan terhadap fluktuasi harga global, embargo, dan gangguan logistik internasional. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bergantung kepada pihak luar dalam hal-hal mendasar seperti makanan dan energi. Dengan memperkuat produksi lokal, umat Islam dapat menjaga keberlanjutan ekonomi dan menghindari ketimpangan yang disebabkan oleh dominasi pasar global. Prinsip ini selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl).
Pemberdayaan sektor pertanian menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis Islam. Petani perlu didukung tidak hanya dengan modal finansial, tetapi juga dengan transfer teknologi, pelatihan manajemen, dan akses terhadap pasar yang adil. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau bank syariah dapat memainkan peran strategis melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem keuangan syariah menghindari praktik riba yang membebani petani, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antara pemodal dan pelaku usaha. Dengan dukungan yang tepat, pertanian bukan hanya sektor tradisional, tetapi motor ekonomi yang produktif dan bernilai sosial tinggi.
Konsep koperasi tani berbasis syariah juga sangat relevan untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip ta’āwun (tolong-menolong), musyārakah (kerja sama), dan iṣlāḥ (perbaikan sosial), yang mengutamakan kemaslahatan bersama di atas keuntungan pribadi. Melalui koperasi, para petani dapat mengakses peralatan modern, membeli pupuk dalam jumlah besar dengan harga terjangkau, serta memasarkan hasil panen secara kolektif untuk mendapatkan nilai jual yang lebih baik. Model ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang keadilan distributif dan solidaritas ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap fluktuasi ekonomi global.
Kemandirian pangan juga memiliki dimensi sosial yang mendalam. Ketika individu dan komunitas memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga merdeka secara moral. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan eksternal yang dapat melemahkan nilai dan kedaulatan umat. Hal ini penting karena ketergantungan ekonomi sering kali menjadi pintu masuk bagi ketergantungan ideologis dan politik. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari jihad ekonomi—sebuah perjuangan untuk menegakkan kemuliaan umat melalui kesejahteraan dan kedaulatan sumber daya.
Selain dimensi ekonomi dan sosial, kemandirian pangan juga mencakup aspek etika dan spiritual. Islam menuntun umatnya untuk hidup dalam keseimbangan antara produksi dan konsumsi, antara kerja keras dan rasa cukup (qanā‘ah). Kemandirian sejati bukan berarti menimbun sumber daya, tetapi mengelolanya dengan bijak dan adil. Dalam hal ini, pendidikan moral dan kesadaran kolektif berperan penting. Umat Islam harus menumbuhkan rasa cinta terhadap produk lokal, menghargai hasil petani, dan menghindari gaya hidup konsumtif yang merusak keseimbangan ekonomi nasional. Setiap pilihan konsumsi harus mencerminkan nilai-nilai keberkahan dan keberlanjutan.
Lebih jauh, solidaritas dunia merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan oleh Islam. Prinsip rahmatan lil ‘ālamīn menempatkan umat Islam bukan hanya sebagai komunitas yang mencari keselamatan individual, tetapi juga sebagai agen pembawa rahmat bagi seluruh makhluk. Dalam konteks krisis pangan global, prinsip ini menuntut partisipasi aktif umat Islam dalam mengatasi kelaparan dan ketimpangan distribusi pangan di berbagai belahan dunia. Solidaritas ini tidak terbatas pada hubungan sesama Muslim, melainkan meluas kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Dengan demikian, kontribusi umat Islam dalam bidang pangan menjadi wujud pengamalan nilai kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan universal.
Dalam era globalisasi, krisis pangan tidak bisa dipandang sebagai persoalan lokal atau nasional semata, melainkan sebagai isu global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Ketika satu wilayah mengalami kekeringan atau konflik yang menghambat produksi pangan, dampaknya dapat merembet ke negara lain melalui kenaikan harga dan gangguan pasokan. Oleh karena itu, tanggung jawab moral umat Islam menuntut adanya solidaritas dunia yang konkret, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, penghapusan hambatan perdagangan, maupun kolaborasi riset dan inovasi teknologi pangan. Islam mengajarkan bahwa membantu sesama manusia yang kelaparan adalah bagian dari ibadah dan bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah SWT.
Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dalam sistem pangan global. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara dan Afrika Utara, banyak wilayah Muslim yang memiliki lahan pertanian subur, sumber daya air melimpah, dan populasi muda yang produktif. Namun, potensi ini sering kali belum terkelola secara optimal karena lemahnya koordinasi, keterbatasan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada sektor pangan. Islam mendorong penguatan kolaborasi antarnegara Muslim untuk saling melengkapi kekuatan tersebut, baik dalam hal sumber daya alam, keuangan, maupun keilmuan, sehingga tercipta kemandirian pangan dunia Islam yang tidak bergantung pada kekuatan ekonomi global Barat.
Sinergi riset dan inovasi teknologi merupakan pilar penting dalam mewujudkan solidaritas dunia Islam di bidang pangan. Negara-negara Muslim dapat mengembangkan pusat-pusat riset internasional yang fokus pada inovasi agrikultur halal, teknologi pengolahan pangan berkelanjutan, dan rekayasa lingkungan untuk pertanian cerdas. Dengan menggabungkan keunggulan akademik dan sumber daya alam yang dimiliki, dunia Islam berpotensi melahirkan sistem pangan yang efisien, etis, dan ramah lingkungan. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat pertukaran pengetahuan antaruniversitas Islam, mempercepat transformasi teknologi, dan memperluas dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat miskin di pedesaan.
Selain riset dan inovasi, kebijakan perdagangan yang adil juga menjadi aspek krusial dalam memperkuat solidaritas global. Banyak negara berkembang, termasuk negara Muslim, mengalami ketimpangan akibat sistem perdagangan dunia yang tidak seimbang. Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan monopoli yang merugikan pihak lemah. Oleh karena itu, negara-negara Muslim perlu memperjuangkan model perdagangan internasional yang berlandaskan keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Dengan menjalin perjanjian dagang yang saling menguntungkan, menghapus hambatan ekspor produk pangan, dan memperkuat kerja sama logistik, dunia Islam dapat memainkan peran signifikan dalam menstabilkan pasokan pangan global.
Inisiatif kolaboratif lintas negara Muslim juga berpotensi melahirkan jejaring solidaritas yang strategis dan berkelanjutan. Melalui organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB), negara-negara anggota dapat membentuk Islamic Food Security Alliance atau aliansi ketahanan pangan Islam. Aliansi ini dapat bertugas mengoordinasikan bantuan pangan lintas negara, mendukung proyek pertanian lintas wilayah, serta memperkuat cadangan pangan strategis bersama. Dengan mekanisme seperti ini, dunia Islam tidak hanya menunjukkan solidaritas simbolik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan global.
Prinsip solidaritas juga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap negara-negara non-Muslim yang mengalami krisis pangan. Islam mengajarkan nilai ihsān (berbuat kebaikan) tanpa batas, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membantu siapa pun yang membutuhkan. Ketika dunia Islam menjadi aktor aktif dalam pemberian bantuan pangan lintas agama dan bangsa, hal itu akan memperkuat citra Islam sebagai agama kasih sayang dan perdamaian. Tindakan ini tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga strategis dalam membangun dialog antarperadaban dan menumbuhkan rasa saling percaya di tengah dunia yang sering terpecah oleh konflik dan kepentingan politik.
Krisis pangan global menyoroti bukan hanya aspek produksi dan distribusi pangan, tetapi juga pola konsumsi masyarakat yang kian tidak seimbang. Dalam konteks ini, masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merefleksikan kembali perilaku konsumsi mereka. Islam menegaskan bahwa konsumsi bukanlah sekadar aktivitas memenuhi kebutuhan fisik, melainkan bagian dari ibadah yang mencerminkan kesyukuran kepada Allah. Oleh karena itu, perilaku konsumtif yang berlebihan, pemborosan makanan, dan ketergantungan pada gaya hidup mewah merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (i‘tidāl) dan kesederhanaan (wasatiyyah).
Prinsip qana‘ah (merasa cukup) menjadi kunci utama dalam mengatur perilaku konsumsi umat Islam. Qana‘ah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah yang dikonsumsi, tetapi oleh kemampuan untuk bersyukur dan hidup dalam batas kebutuhan yang wajar. Dalam konteks krisis pangan global, menerapkan nilai qana‘ah berarti menghindari pemborosan makanan, mengurangi konsumsi barang impor yang tidak perlu, serta mendukung produk lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, pola hidup sederhana tidak hanya membawa ketenangan spiritual, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan pangan dan keadilan sosial.
Selain qana‘ah, konsep zuhd juga relevan dalam membentuk kesadaran konsumsi di tengah masyarakat modern yang materialistik. Zuhd bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan menempatkan dunia pada posisi yang proporsional — tidak menjadi pusat perhatian atau sumber keserakahan. Dalam konsumsi pangan, sikap zuhud berarti memilih makanan yang sehat, halal, dan bermanfaat (thayyib), bukan sekadar mengikuti tren atau selera yang berlebihan. Rasulullah SAW mencontohkan gaya hidup yang sangat sederhana, bahkan dalam kelimpahan. Beliau makan secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu mengingatkan umatnya bahwa sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas.
Krisis pangan global seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat kesadaran konsumsi yang beretika. Mengonsumsi produk halal-thayyib bukan hanya persoalan hukum syariah, tetapi juga bentuk partisipasi dalam menjaga keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Produk halal-thayyib mengandung dimensi keadilan—dihasilkan tanpa eksploitasi lingkungan, tanpa penindasan terhadap pekerja, dan tanpa merusak keseimbangan alam. Ketika umat Islam memilih produk yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan, mereka sesungguhnya sedang ikut menegakkan prinsip maṣlaḥah ‘āmmah (kemaslahatan umum) yang menjadi inti dari maqāṣid al-syarī‘ah.
Perubahan pola konsumsi juga membutuhkan pendekatan struktural melalui pendidikan, kebijakan publik, dan dakwah sosial. Sekolah, masjid, dan lembaga keagamaan dapat berperan penting dalam menanamkan nilai konsumsi etis sejak dini. Pemerintah dapat mendorong kebijakan yang mengurangi pemborosan pangan, memperkuat rantai pasok lokal, dan memberi insentif bagi produk ramah lingkungan. Sementara itu, para ulama dan dai dapat mengintegrasikan pesan moral tentang kesederhanaan dan keberlanjutan ke dalam khutbah, kajian, dan kampanye publik. Upaya kolektif ini akan menciptakan budaya konsumsi baru yang lebih seimbang dan berorientasi pada tanggung jawab sosial.
Di era digital, kampanye kesadaran konsumsi etis dapat menjadi gerakan sosial yang kuat. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya gaya hidup hemat, anti-pemborosan, dan penghargaan terhadap sumber daya alam. Umat Islam dapat menjadi pionir dalam menciptakan tren konsumsi yang bukan hanya modis, tetapi juga bermakna — seperti gerakan “zero waste halal” atau “eco-halal lifestyle” yang memadukan nilai religius dengan kesadaran ekologis. Kampanye semacam ini dapat mengubah paradigma masyarakat dari konsumsi tanpa batas menjadi konsumsi yang berorientasi pada keberkahan dan keberlanjutan.
Krisis pangan global juga memperlihatkan paradoks dunia modern: di satu sisi ada kelebihan pangan yang terbuang, sementara di sisi lain jutaan orang kelaparan. Dalam pandangan Islam, situasi seperti ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diatasi. Allah melarang pemborosan dalam segala bentuknya, sebagaimana termaktub dalam Surah al-A‘rāf ayat 31: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Ayat ini bukan hanya peringatan moral, tetapi juga prinsip etika ekonomi dan ekologi. Menghindari pemborosan berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya, antara hak individu dan tanggung jawab sosial.
Pada akhirnya, ketahanan pangan dalam Islam bukan hanya persoalan ketersediaan makanan, melainkan cerminan dari keimanan, etika, dan solidaritas global. Krisis pangan menuntut perubahan paradigma dari kompetisi menuju kolaborasi, dari eksploitasi menuju pelestarian, serta dari kepentingan individu menuju kepedulian universal. Dalam perspektif Islam, keberhasilan mengatasi krisis pangan dunia bukan diukur dari banyaknya produksi semata, tetapi dari sejauh mana nilai keadilan, keberlanjutan, dan kasih sayang diwujudkan dalam sistem pangan global. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari, umat Muslim dapat menjadi pelopor dalam membangun dunia yang berkeadilan pangan dan berkelanjutan.