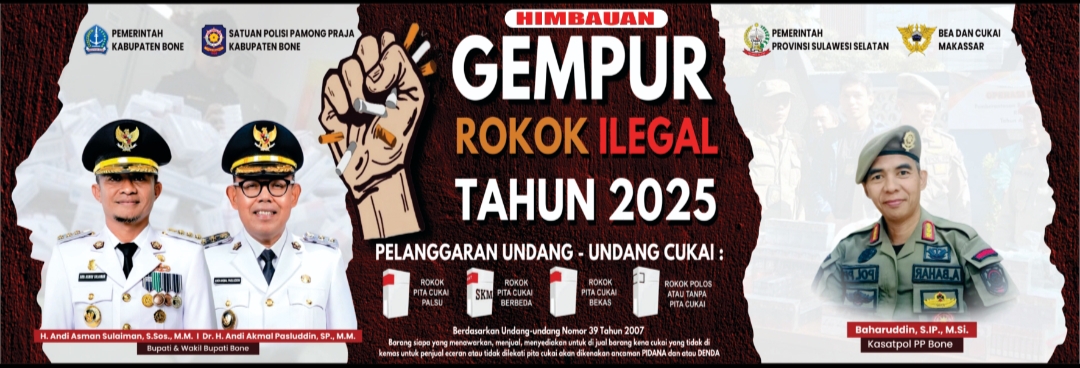Oleh: Prof. Syaparuddin, Guru Besar IAIN Bone dalam Ekonomi Syariah
PERTANIAN berbasis maslahah merupakan konsep yang menempatkan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya agraria. Maslahah di sini bukan hanya dimaknai sebagai keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan mencakup keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan distribusi hasil pertanian. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberi manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Dalam konteks pertanian berbasis maslahah, nilai-nilai syariah menjadi landasan moral dan etis yang menuntun setiap aktivitas manusia dalam mengelola alam. Islam menegaskan bahwa bumi adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan prinsip maslahah mengajarkan bahwa kegiatan pertanian bukan hanya sekadar upaya mencari keuntungan materi, melainkan juga bentuk ibadah yang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kemanfaatan jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan cara pandang ini, pertanian menjadi bagian integral dari upaya menegakkan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa, harta, dan keturunan.
Pemanfaatan lahan yang tidak berlebihan menjadi salah satu prinsip penting dalam pertanian berbasis maslahah. Islam menolak praktik eksploitatif yang dapat mengakibatkan kerusakan lahan, deforestasi, atau alih fungsi lahan secara masif tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Penggunaan lahan harus mempertahankan daya dukung ekosistem, misalnya dengan menjaga hutan lindung, memelihara daerah resapan air, dan mengatur pola tanam sesuai kapasitas tanah. Dengan menjaga keseimbangan ini, pertanian tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga melestarikan fungsi ekologis yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam praktik pertanian juga merupakan wujud nyata integrasi nilai syariah dengan pembangunan berkelanjutan. Islam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat, sehingga inovasi seperti pertanian organik, sistem irigasi hemat air, dan teknologi energi terbarukan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pertanian yang efisien dan berdaya saing. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga mencerminkan semangat Islam dalam mendorong kemajuan yang selaras dengan kelestarian alam.
Pola tanam yang mendukung keberagaman ekosistem juga menjadi pilar dalam pertanian berbasis maslahah. Islam menghargai keberagaman ciptaan Allah, sehingga penerapan monokultur yang berlebihan dan merusak keseimbangan ekologis sebaiknya dihindari. Sebaliknya, penerapan pola tanam campuran, rotasi tanaman, dan integrasi peternakan dengan pertanian dapat menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko hama, serta meningkatkan ketahanan pangan. Dengan cara ini, pertanian tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat ekologi yang lebih luas bagi keberlanjutan kehidupan.
Larangan terhadap israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan) menjadi dasar moral dalam pengelolaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan air. Islam menegaskan bahwa segala sesuatu harus digunakan sesuai kebutuhan dan tidak boleh melewati batas yang bisa menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida sebaiknya dibatasi dengan mengganti atau memadukannya dengan pupuk organik dan metode pengendalian hayati. Demikian pula, pemanfaatan air irigasi harus dilakukan secara hemat, misalnya melalui sistem irigasi tetes atau pengelolaan air berbasis komunitas. Dengan langkah ini, pertanian dapat berkontribusi dalam menjaga sumber daya alam agar tetap lestari.
Maslahah dalam pertanian tidak hanya diukur dari seberapa besar hasil panen atau keuntungan yang diperoleh, melainkan dari bagaimana kegiatan tersebut menjaga kelestarian sumber daya. Produktivitas yang tinggi namun merusak tanah dan air pada akhirnya tidak membawa keberkahan, karena bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan kemanfaatan berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan pertanian berbasis maslahah harus dilihat secara komprehensif, yakni mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, konsep ini lebih holistik dibandingkan pendekatan pertanian modern yang hanya berorientasi pada produktivitas semata.
Pertanian berbasis maslahah juga memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari sekadar praktik agrikultural biasa. Petani yang mengelola tanah dengan penuh kesadaran syariah bukan hanya sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga sedang menunaikan amanah ilahi. Setiap benih yang ditanam, setiap tetes air yang digunakan dengan bijaksana, dan setiap hasil panen yang dibagikan secara adil, semuanya bernilai ibadah. Dimensi ini memberikan motivasi moral yang kuat bagi petani untuk menjaga etika dalam produksi, menghindari kerusakan, dan memastikan manfaat pertanian dirasakan secara luas.
Konsep maslahah dalam pertanian yang menekankan aspek keadilan sosial berangkat dari prinsip dasar Islam bahwa setiap rezeki yang diturunkan Allah harus membawa manfaat seluas-luasnya bagi umat manusia. Pertanian sebagai sumber utama pangan tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar, melainkan harus menjadi penopang kehidupan bersama. Keadilan sosial dalam hal ini dimaknai sebagai distribusi hasil pertanian yang seimbang, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pemilik lahan luas dan petani kecil yang bekerja keras di lapangan. Dengan pendekatan ini, pertanian tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Prinsip distribusi yang adil dalam Islam tercermin dari kewajiban zakat hasil pertanian yang harus ditunaikan setiap kali panen. Zakat bukan sekadar ritual ibadah, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang mampu menjembatani kesenjangan antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Dalam praktiknya, hasil panen yang dizakati akan menjadi sumber pangan bagi masyarakat miskin, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini sejalan dengan tujuan maslahah, yakni menciptakan manfaat bersama dan menghindarkan masyarakat dari bahaya kelaparan serta ketidakadilan.
Selain zakat, Islam juga mendorong infaq dan sedekah sebagai bentuk distribusi sukarela yang memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat agraris. Petani yang memiliki kelebihan hasil panen dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tradisi berbagi hasil pertanian ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan cara demikian, hasil pertanian yang melimpah tidak menimbulkan kesenjangan, melainkan memperkuat jaringan sosial yang harmonis dan berdaya tahan.
Keadilan sosial dalam pertanian berbasis maslahah juga menuntut adanya pengakuan atas peran penting buruh tani. Mereka adalah tenaga kerja yang menggerakkan roda produksi, sehingga kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan. Islam menekankan pentingnya memberikan upah yang layak dan adil, sesuai dengan kerja keras yang telah mereka lakukan. Jika buruh tani hidup dalam kesejahteraan, maka stabilitas sosial dan produktivitas pertanian akan terjaga. Dengan demikian, keadilan sosial tidak berhenti pada distribusi hasil panen, tetapi juga mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan sepanjang rantai produksi.
Lebih jauh, konsep maslahah menegaskan bahwa akses pangan yang merata merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai jika hanya segelintir pihak yang dapat menikmati hasil pertanian, sementara sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, distribusi hasil pertanian harus diatur sedemikian rupa agar mampu menjangkau semua lapisan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Pemerataan ini tidak hanya menjawab kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik yang lahir dari ketimpangan ekonomi.
Dalam Islam, distribusi yang adil juga berfungsi untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Al-Qur’an menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di antara orang-orang kaya saja, melainkan harus beredar luas untuk memberi manfaat kepada semua. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pertanian, di mana monopoli lahan dan modal sering kali menjadi penyebab utama ketidakadilan. Dengan mengedepankan maslahah, kebijakan pertanian harus diarahkan untuk mencegah monopoli, melindungi petani kecil, dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya.
Keadilan sosial dalam pertanian juga berimplikasi pada keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat nasional. Ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, sehat, dan halal, maka stabilitas sosial dan politik pun akan terjaga. Sebaliknya, jika distribusi hasil pertanian timpang, maka kerawanan pangan dapat memicu gejolak sosial yang merugikan semua pihak. Dengan menempatkan maslahah sebagai orientasi utama, sistem pertanian dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga harmoni sosial.
Pertanian berbasis maslahah yang mendukung diversifikasi pangan berangkat dari kesadaran bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya bertumpu pada satu jenis komoditas. Dalam perspektif Islam, menjaga keseimbangan dalam konsumsi merupakan bagian dari ajaran untuk menghindari sikap berlebih-lebihan dan membiasakan diri pada pola hidup sehat. Diversifikasi pangan bukan hanya soal variasi produk, tetapi juga strategi untuk memastikan setiap individu memperoleh gizi seimbang dari sumber makanan yang beragam. Dengan adanya variasi pangan, masyarakat dapat terhindar dari malnutrisi sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Konsep diversifikasi pangan sangat relevan dalam menghadapi risiko gagal panen pada satu komoditas tertentu. Ketika masyarakat terlalu bergantung pada satu jenis bahan makanan, kerentanan akan meningkat jika terjadi bencana alam, perubahan iklim, atau serangan hama. Dalam konteks inilah, pertanian berbasis maslahah mendorong pengembangan berbagai jenis tanaman, baik pangan pokok, hortikultura, maupun tanaman alternatif yang memiliki nilai gizi tinggi. Upaya ini tidak hanya memperkaya pilihan konsumsi, tetapi juga memberikan cadangan pangan yang lebih stabil untuk menghadapi situasi darurat.
Diversifikasi pangan juga memiliki dimensi ekonomi yang sejalan dengan tujuan maslahah. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang stabil, karena tidak seluruh komoditas bergantung pada satu siklus pasar. Jika harga satu produk turun, petani masih memiliki alternatif lain yang bisa dijual. Hal ini mengurangi risiko kerugian sekaligus menciptakan jaring pengaman ekonomi bagi para pelaku pertanian. Dalam jangka panjang, strategi ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi pedesaan.
Dari sisi ekologi, diversifikasi pangan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sistem pertanian monokultur yang hanya mengandalkan satu jenis tanaman sering kali membuat tanah cepat rusak, mengurangi kesuburan, dan meningkatkan kerentanan terhadap hama. Sebaliknya, dengan menerapkan rotasi tanaman atau menanam beragam komoditas dalam satu lahan, kesuburan tanah dapat terjaga, hama dapat ditekan secara alami, dan keanekaragaman hayati tetap lestari. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta menghindari kerusakan lingkungan.
Diversifikasi pangan dalam pertanian berbasis maslahah juga memperkuat prinsip halal dan thayyib. Islam tidak hanya menuntut makanan yang halal secara hukum, tetapi juga thayyib, yakni baik, sehat, dan bermanfaat. Dengan adanya variasi pangan, masyarakat lebih mudah mendapatkan makanan bergizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup umat, karena ketahanan pangan yang kuat tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas makanan yang dikonsumsi.
Selain itu, diversifikasi pangan memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi ketergantungan pada impor. Ketika masyarakat mampu memproduksi berbagai jenis bahan pangan di dalam negeri, ketahanan pangan tidak akan rapuh meski terjadi gejolak harga global. Prinsip ini sejalan dengan semangat Islam yang menekankan kemandirian dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Dengan demikian, pertanian berbasis maslahah melalui diversifikasi pangan bukan hanya menjaga keseimbangan konsumsi, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Strategi diversifikasi pangan juga mendorong inovasi dalam pengembangan produk pertanian. Petani dan pelaku usaha pangan dapat mengolah berbagai hasil pertanian menjadi produk turunan bernilai tambah, sehingga membuka peluang pasar baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkaya pilihan makanan masyarakat. Dalam kerangka maslahah, inovasi ini menjadi bagian dari upaya menciptakan manfaat luas bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam secara optimal dan bijaksana.
Konsep pemberdayaan petani dalam kerangka pertanian berbasis maslahah menegaskan bahwa petani adalah aktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Mereka bukan sekadar pelaku produksi, tetapi juga penjaga keseimbangan ekologi dan penopang kesejahteraan masyarakat luas. Islam menempatkan peran petani dalam posisi mulia, karena melalui kerja keras mereka kebutuhan dasar umat dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pemberdayaan petani menjadi langkah penting agar mereka tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemandirian, keterampilan, dan daya tawar yang kuat dalam sistem pangan.
Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan adalah salah satu bentuk implementasi maslahah. Petani perlu dibekali dengan pengetahuan tentang teknik budidaya modern, manajemen usaha tani, hingga pengolahan pascapanen agar mampu bersaing di era global. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, dan dalam konteks pertanian, hal ini berarti memperkuat pemahaman petani terhadap cara mengelola tanah dan hasil panen secara optimal. Pelatihan yang berkelanjutan juga dapat membuka wawasan petani mengenai praktik ramah lingkungan yang selaras dengan nilai syariah.
Selain pelatihan, akses teknologi juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan petani. Teknologi pertanian seperti sistem irigasi modern, penggunaan benih unggul, hingga aplikasi digital untuk pemasaran hasil panen dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Islam tidak menolak kemajuan teknologi selama membawa kemaslahatan, sehingga inovasi pertanian yang mendukung keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan prinsip syariah. Akses teknologi yang merata bagi petani kecil akan mengurangi kesenjangan dengan pemilik modal besar, sehingga tercipta keadilan dalam sistem pangan.
Penguatan kelembagaan pertanian juga tidak kalah penting dalam kerangka pemberdayaan petani. Kelembagaan yang kuat, seperti koperasi tani atau kelompok usaha bersama, memungkinkan petani untuk memperoleh akses modal, memperluas jaringan pasar, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Islam menekankan pentingnya ukhuwah dan kerja sama dalam membangun kekuatan bersama, sehingga kelembagaan pertanian dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas antarpetani. Dengan adanya wadah kolektif, posisi petani di pasar akan lebih kuat dan mereka tidak mudah dieksploitasi oleh tengkulak atau pihak-pihak yang merugikan.
Transformasi sosial-ekonomi yang berkeadilan hanya dapat tercapai jika petani diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Selama ini, petani kecil sering kali berada pada posisi lemah karena keterbatasan modal, akses informasi, dan pasar. Pertanian berbasis maslahah hadir untuk mengoreksi ketidakadilan ini dengan menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemberdayaan yang tepat, petani tidak hanya keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghindarkan masyarakat dari kemudaratan.
Dimensi spiritual juga tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan petani. Islam memandang bekerja di sektor pertanian sebagai amal shaleh yang bernilai ibadah, terutama jika dilakukan dengan niat untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Ketekunan petani dalam mengelola bumi mencerminkan perintah Allah untuk berusaha (ikhtiar) dengan sungguh-sungguh. Dengan bekal ilmu dan keterampilan, petani bukan hanya menjadi pengelola lahan, tetapi juga pelaksana amanah ilahi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Hal ini memberikan makna yang lebih dalam terhadap upaya pemberdayaan yang dijalankan.
Pemberdayaan petani juga memiliki efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Petani yang berdaya akan mampu menghasilkan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara langsung memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan petani bukan hanya kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga kepentingan strategis bangsa. Dalam kerangka maslahah, hal ini merupakan bentuk nyata menjaga kemaslahatan umum dengan memberdayakan pilar utama sistem pangan.
Konsep maslahah yang menekankan pentingnya kedaulatan pangan merupakan prinsip mendasar dalam menjaga ketahanan bangsa. Pangan adalah kebutuhan vital yang tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh pihak luar, karena hal ini akan menempatkan masyarakat pada posisi yang rentan. Ketergantungan berlebihan terhadap impor membuat suatu negara mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga global, kebijakan negara pengekspor, maupun gangguan rantai pasok internasional. Dalam perspektif Islam, kondisi ini dapat membahayakan kemaslahatan umat karena mengancam keberlangsungan hidup masyarakat secara luas.
Islam mendorong kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagai bagian dari menjaga maqasid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Pangan yang cukup dan terjangkau adalah syarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan hidup, sementara stabilitas harga pangan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan menjadi bagian penting dari upaya menegakkan maslahah, karena dengannya masyarakat terbebas dari tekanan eksternal yang dapat merugikan stabilitas ekonomi maupun sosial.
Penguatan produksi lokal berbasis sumber daya domestik adalah strategi utama untuk mencapai kedaulatan pangan yang sesuai dengan nilai Islam. Pemanfaatan lahan pertanian dalam negeri, pemberdayaan petani lokal, serta pengembangan teknologi tepat guna memungkinkan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dengan demikian, keberlanjutan sistem pangan tidak hanya ditopang oleh pasar global, tetapi juga berdiri kokoh di atas potensi domestik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk mengoptimalkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada suatu bangsa dalam bentuk tanah subur, iklim yang mendukung, serta kekayaan hayati yang berlimpah.
Kedaulatan pangan yang berbasis produksi lokal juga memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Sektor pertanian yang kuat mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di pedesaan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi pangan, tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan ekonomi keluarga petani meningkat. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana pertanian berbasis maslahah tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja yang adil.
Selain aspek ekonomi, kedaulatan pangan juga berhubungan erat dengan stabilitas politik nasional. Sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan sering kali memicu gejolak sosial, bahkan keruntuhan sebuah pemerintahan. Negara yang tidak mampu menyediakan pangan bagi rakyatnya akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Dengan memperkuat produksi pangan dalam negeri, stabilitas politik dapat lebih terjaga karena kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Prinsip ini selaras dengan nilai maslahah, di mana keamanan dan stabilitas merupakan prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan bersama.
Islam juga mengajarkan prinsip kemandirian sebagai bentuk kehormatan bagi umat. Bergantung pada pihak luar dalam hal-hal vital dianggap sebagai kelemahan yang dapat membuka pintu dominasi. Dalam konteks pangan, ketergantungan pada impor berarti menyerahkan kendali kebutuhan pokok kepada pihak asing. Oleh karena itu, upaya memperkuat kedaulatan pangan bukan hanya persoalan teknis ekonomi, tetapi juga persoalan identitas dan martabat bangsa. Maslahah dalam hal ini menuntut agar bangsa Muslim memiliki ketahanan yang kokoh dengan mengurangi ketergantungan eksternal secara signifikan.
Lebih jauh, strategi kedaulatan pangan yang sesuai dengan nilai maslahah juga mendorong pengembangan kebijakan nasional yang pro-petani dan berorientasi pada keberlanjutan. Subsidi input pertanian, perlindungan harga panen, serta pengendalian impor yang tidak merugikan petani lokal adalah kebijakan konkret yang sejalan dengan prinsip maslahah. Dengan menciptakan iklim yang mendukung bagi petani, negara tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membangun fondasi sosial-ekonomi yang kuat dan mandiri.
Secara keseluruhan, pertanian berbasis maslahah adalah paradigma yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama, strategi ini dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan kontemporer, mulai dari perubahan iklim, kerawanan pangan, hingga ketidakadilan distribusi. Islam memandang pangan sebagai hak dasar manusia yang harus dipenuhi secara adil, sehat, dan berkelanjutan, sehingga pertanian berbasis maslahah dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh.