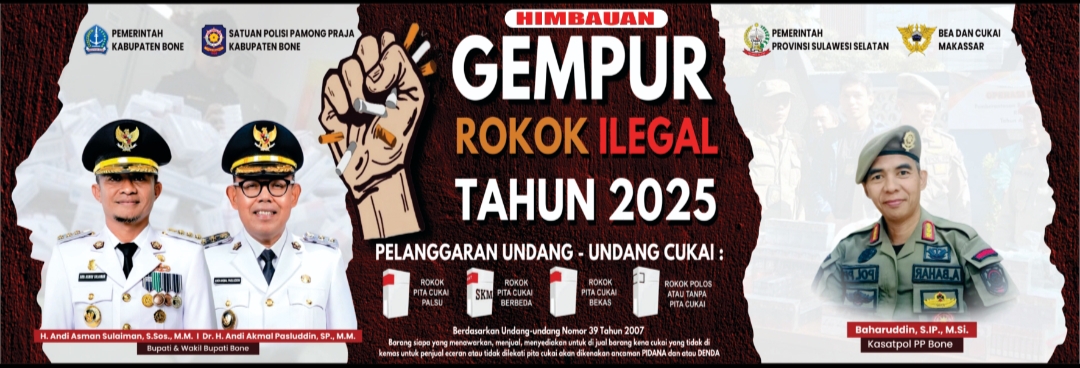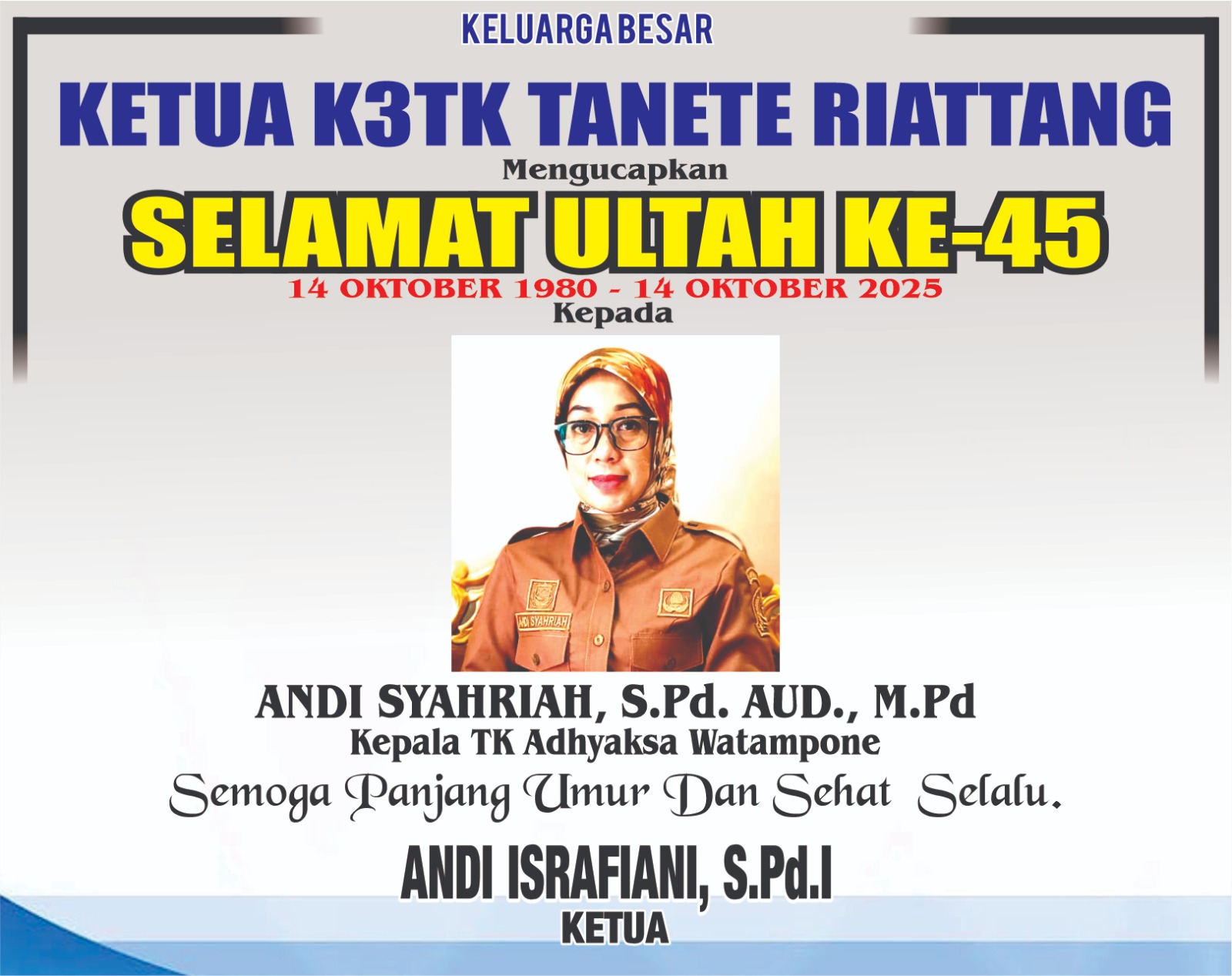Oleh: Prof. Syaparuddin, Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
DEMO PBB-P2 yang merebak di daerah menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keresahan ini berakar pada perasaan ketidakadilan yang dirasakan warga, di mana pajak yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru dianggap membebani kehidupan rakyat kecil. Secara konseptual, pajak dalam bingkai Islam dikenal sebagai bagian dari kewajiban kolektif (kifayah) untuk mendukung kemaslahatan umum. Namun, prinsip yang harus dijaga adalah keadilan distribusi dan tidak adanya unsur yang menjerat atau memberatkan masyarakat, terutama kalangan lemah. Fakta di lapangan menunjukkan, kenaikan PBB-P2 sering tidak disertai dengan mekanisme sosialisasi yang jelas maupun pertimbangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam tradisi Islam, kharaj dan jizyah merupakan instrumen fiskal yang dikenal sejak masa Rasulullah SAW hingga masa Khulafā’ al-Rāsyidīn. Kharaj dipungut atas tanah yang dimiliki non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam, sedangkan jizyah adalah pungutan bagi non-Muslim sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Kedua bentuk pungutan ini bukan sekadar upaya menambah kas negara, melainkan sarana untuk menjaga stabilitas, memelihara keadilan, serta menjamin hak hidup seluruh masyarakat. Dengan demikian, pajak dalam Islam pada hakikatnya tidak pernah dimaksudkan sebagai beban, melainkan sebagai wujud partisipasi sosial demi tercapainya kemaslahatan bersama.
Rasulullah SAW mencontohkan praktik fiskal yang sarat dengan nilai keadilan. Beliau selalu menimbang kemampuan pihak yang dikenakan kewajiban, bahkan seringkali memberi keringanan jika kondisi ekonomi rakyat sedang sulit. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, keadilan pajak bukan hanya dalam aspek jumlah, tetapi juga dalam prinsip proporsionalitas. Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat kemampuan seseorang agar tidak menimbulkan kesenjangan dan penderitaan. Kebijakan semacam ini sejalan dengan etika keuangan Islam yang mengedepankan asas rahmah (kasih sayang) dan ta‘āwun (tolong-menolong).
Kebijakan fiskal yang dijalankan para khalifah setelah Rasulullah SAW juga memperkuat prinsip tersebut. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, terkenal sangat berhati-hati dalam menetapkan pajak. Ia bahkan menghapus atau meringankan beban pajak di daerah-daerah yang mengalami bencana, kekeringan, atau gagal panen. Tindakan ini memperlihatkan bahwa pajak bukanlah kewajiban yang bersifat kaku, melainkan instrumen yang fleksibel dan harus menyesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Konsep inilah yang membedakan sistem perpajakan Islam dengan banyak sistem konvensional modern yang sering kali kurang memperhatikan aspek kemanusiaan.
Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī‘ah, pungutan pajak dalam Islam diarahkan untuk melindungi kepentingan vital masyarakat. Perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) menjadi alasan utama agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan perampasan secara halus melalui pajak yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan perlindungan terhadap kehidupan (ḥifẓ al-nafs), di mana pajak yang adil akan memastikan rakyat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila pajak memberatkan hingga mengganggu kelangsungan hidup, maka hal itu bertentangan dengan prinsip maqāṣid yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariat.
Kharaj dan jizyah dalam sejarah Islam juga diposisikan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Hasil pungutan tidak hanya masuk ke kas negara untuk kepentingan penguasa, tetapi dialokasikan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan menjaga keamanan. Dengan cara ini, pajak menjadi sarana pemerataan yang memperkuat solidaritas sosial. Negara dalam Islam tidak boleh bersikap eksploitatif, melainkan berfungsi sebagai pengelola amanah untuk memastikan bahwa harta yang dikumpulkan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata.
Konsep ini memberi pelajaran berharga bagi sistem perpajakan modern, termasuk dalam konteks PBB-P2. Jika kenaikan pajak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, maka hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pajak yang terlalu tinggi hanya akan memperburuk kesenjangan dan memunculkan gejolak sosial. Sebaliknya, apabila kebijakan pajak disusun dengan dasar keadilan dan diarahkan untuk kemaslahatan umum, maka ia akan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Di sinilah prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dapat menjadi rujukan etis sekaligus praktis dalam perumusan kebijakan fiskal.
Keterhubungan antara pajak dan kemaslahatan dalam Islam juga mengandung pesan moral bahwa negara wajib transparan dan akuntabel. Rasulullah SAW dan para khalifah tidak hanya mengumpulkan pajak, tetapi juga memastikan penggunaannya untuk kepentingan rakyat. Transparansi inilah yang membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Jika rakyat melihat manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, mereka tidak akan merasa terbebani, melainkan justru bangga dapat berkontribusi bagi pembangunan bersama.
Kenaikan PBB-P2 di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari konteks desentralisasi fiskal yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Pajak ini kemudian menjadi salah satu instrumen utama untuk menambah penerimaan daerah. Akan tetapi, ketika kebijakan fiskal dijalankan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, maka ia berubah menjadi beban sosial yang meresahkan. Islam menegaskan bahwa pajak hanya sah secara moral apabila digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan sekadar memenuhi target penerimaan kas daerah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak dalam penerapannya.
Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal adalah amanah yang melekat pada fungsi negara sebagai pengelola kesejahteraan. Transparansi berarti pemerintah wajib menjelaskan secara jujur tujuan, mekanisme, dan manfaat dari pajak yang dipungut. Sementara akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas mengenai ke mana dana pajak dialokasikan. Jika kenaikan PBB-P2 tidak diiringi dengan perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, masyarakat akan menilai kebijakan tersebut cacat secara moral. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara tujuan formal kebijakan fiskal dengan realitas yang dirasakan rakyat.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam Islam dipandang sebagai amanah yang tidak boleh dikhianati. Al-Qur’an mengingatkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak, termasuk amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Ketika masyarakat merasa pajak yang dibayarkan tidak kembali dalam bentuk manfaat, mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Rasa ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, bahkan protes, sebagaimana terlihat dalam demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah. Dalam konteks ini, krisis kepercayaan merupakan dampak serius yang harus diantisipasi melalui perbaikan tata kelola fiskal.
Islam menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik. Ketika pemerintah menjaga amanah dengan mengelola pajak secara adil dan transparan, rakyat akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika pajak dianggap sekadar instrumen untuk memperbesar penerimaan tanpa adanya manfaat yang nyata, maka rakyat akan merasa dieksploitasi. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, tetapi juga merusak hubungan antara rakyat dan pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang adil adalah cerminan moralitas kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Lebih jauh lagi, Islam memandang pajak sebagai instrumen yang harus menjawab kebutuhan rakyat. Artinya, setiap kenaikan pajak harus disertai dengan bukti nyata adanya peningkatan kesejahteraan. Jika kenaikan PBB-P2 hanya menghasilkan tambahan penerimaan daerah tanpa perbaikan layanan publik, maka itu adalah bentuk ketidakadilan fiskal. Ketidakadilan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan distribusi kesejahteraan secara merata. Dalam kondisi seperti ini, demo yang dilakukan masyarakat dapat dipahami sebagai ekspresi keprihatinan sekaligus koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umum.
Dengan demikian, persoalan kenaikan PBB-P2 tidak hanya soal fiskal, tetapi juga soal moral dan amanah publik. Islam menegaskan bahwa sebuah kebijakan tidak cukup hanya sah secara hukum positif, tetapi juga harus sah secara etis dan spiritual. Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama yang menentukan legitimasi sebuah kebijakan. Pemerintah daerah yang gagal menjaga nilai-nilai ini akan menghadapi krisis legitimasi, yang dalam konteks demokrasi modern bisa berujung pada resistensi dan hilangnya dukungan rakyat.
Penting untuk dicatat bahwa Islam mendorong adanya keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan ini menuntut adanya mekanisme evaluasi kebijakan pajak yang melibatkan suara rakyat. Musyawarah (shūrā) dalam tradisi Islam memberikan landasan agar kebijakan fiskal tidak lahir secara sepihak, tetapi melalui proses partisipatif yang mencerminkan kepentingan bersama. Dalam hal ini, demo PBB-P2 dapat dilihat sebagai salah satu bentuk shūrā kontemporer, di mana masyarakat menyalurkan aspirasinya untuk menuntut kebijakan yang lebih adil dan maslahat.
Asas keadilan dalam pengenaan pajak merupakan prinsip fundamental yang ditekankan Islam sejak awal. Pajak tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, melainkan harus fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi sosial-ekonomi yang dihadapi rakyat. Prinsip ini terlihat jelas pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang dalam banyak kasus mengambil keputusan untuk mengurangi atau bahkan menghapus kewajiban pajak ketika rakyat berada dalam kondisi sulit. Tindakan ini bukan hanya kebijakan fiskal, tetapi juga wujud nyata dari kepemimpinan yang peka terhadap penderitaan masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan.
Kisah Khalifah Umar sering dijadikan rujukan untuk menegaskan bahwa kebijakan pajak dalam Islam bersifat dinamis dan tidak statis. Ketika terjadi gagal panen, kekeringan, atau bencana alam, Umar memahami bahwa rakyat tidak dalam posisi mampu menunaikan kewajiban fiskal. Memaksakan pajak dalam kondisi demikian hanya akan memperburuk keadaan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, penghapusan pajak sementara bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan kebijakan adaptif yang menegaskan keberpihakan kepada rakyat. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi landasan setiap kebijakan fiskal kontemporer.
Dalam konteks Indonesia, demo yang menolak kenaikan PBB-P2 dapat dipahami sebagai ekspresi moral rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Ketika pajak dinaikkan tanpa memperhatikan daya beli masyarakat atau tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi pasca pandemi, inflasi, atau bencana, rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Protes tersebut bukan sekadar bentuk ketidakpuasan, tetapi juga sinyal bahwa kebijakan fiskal perlu dikaji ulang agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, demonstrasi rakyat merupakan koreksi sosial terhadap kebijakan yang cenderung abai pada nilai keadilan.
Islam menegaskan bahwa pajak harus menjadi sarana untuk mempermudah kehidupan umat, bukan menambah beban yang membuat mereka semakin sulit. Konsep pajak dalam Islam adalah instrumen yang digunakan negara untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan memastikan kesejahteraan merata. Apabila pajak justru dipersepsikan sebagai alat penindasan atau eksploitasi, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moral dan bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus diletakkan pada posisi strategis sebagai instrumen pelayanan, bukan semata-mata penarikan dana.
Asas keadilan dalam pengenaan pajak juga menuntut pemerintah untuk membedakan antara kelompok masyarakat yang kuat dan yang lemah. Kelompok berpenghasilan tinggi seharusnya menanggung beban lebih besar, sementara kelompok miskin perlu diberi keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Prinsip progresivitas ini selaras dengan nilai Islam yang mendorong redistribusi kekayaan dan melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, penerapan asas keadilan bukan hanya soal angka tarif pajak, melainkan juga soal kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Penting untuk dicatat bahwa keadilan pajak tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga oleh transparansi dalam penggunaan dana. Jika rakyat merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, mereka akan dengan sukarela mematuhinya. Namun, jika pajak dirasakan hanya menambah beban tanpa memberi manfaat nyata, resistensi sosial akan semakin kuat. Dalam perspektif Islam, ketidakpercayaan semacam ini menandakan kegagalan pemerintah dalam mengelola amanah fiskal.
Dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang dicontohkan Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif, adil, dan berpihak pada rakyat adalah kunci untuk menciptakan stabilitas sosial. Demo yang muncul akibat kenaikan PBB-P2 seharusnya dipandang sebagai peringatan agar pemerintah kembali menimbang kebijakan dengan perspektif keadilan sosial. Islam memberikan arahan yang jelas bahwa setiap kebijakan fiskal tidak boleh menambah kesulitan rakyat, melainkan harus menjadi solusi untuk mengurangi penderitaan mereka.
Disparitas ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi faktor penting dalam memahami keresahan publik terhadap kenaikan PBB-P2. Banyak kelompok menengah ke bawah yang justru menanggung beban berat akibat pajak ini, sementara kelompok berpenghasilan tinggi relatif lebih leluasa memenuhi kewajiban mereka. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan fiskal, sebab kebijakan pajak semestinya tidak memperlebar jurang kesenjangan sosial. Islam secara tegas menolak adanya praktik yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi beban, karena prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik adalah keadilan dan kemaslahatan.
Dalam Islam, pajak bukan sekadar instrumen fiskal untuk mengisi kas negara, melainkan sarana redistribusi kekayaan. Artinya, pajak harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, bukan sebaliknya. Jika pajak malah membebani kalangan miskin, maka tujuan syariat untuk menjaga keseimbangan sosial tidak tercapai. Sebaliknya, pajak yang adil dan proporsional akan memperkuat rasa kebersamaan, meningkatkan kepercayaan sosial, dan menciptakan stabilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari tujuan syariat.
Ketika pajak diterapkan secara progresif, yakni semakin besar kontribusi bagi mereka yang memiliki harta lebih, maka beban masyarakat miskin akan berkurang. Prinsip ini tidak hanya mendukung pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari keadilan sosial yang diamanahkan Islam. Sayangnya, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa kelompok rentan justru menanggung beban pajak yang sama beratnya dengan kelompok yang lebih mampu. Situasi ini memperlihatkan ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dengan semangat Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.
Di Indonesia sendiri, prinsip gotong royong telah lama menjadi identitas budaya yang sejalan dengan ajaran Islam. Gotong royong menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika nilai ini diterjemahkan ke dalam kebijakan pajak, maka semestinya pajak menjadi instrumen kolektif untuk menopang kesejahteraan bersama. Pajak tidak boleh dimaknai sebagai alat penindasan, melainkan kontribusi sukarela yang disertai rasa percaya bahwa hasilnya akan kembali dalam bentuk layanan publik yang bermanfaat.
Apabila pajak dikelola dengan berorientasi pada redistribusi kekayaan, maka ia akan memperkuat solidaritas sosial. Masyarakat kaya yang berkontribusi lebih besar akan membantu meringankan beban masyarakat miskin, sementara negara bertindak sebagai pengelola amanah yang memastikan dana digunakan untuk kemaslahatan. Dengan demikian, pajak dapat menjadi sarana memperkuat persaudaraan kebangsaan sekaligus mewujudkan cita-cita Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Namun, jika pajak dikelola tanpa prinsip keadilan, ia justru akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan memperbesar kesenjangan sosial. Rakyat kecil akan merasa terpinggirkan, sementara kelompok elit tetap menikmati keuntungan. Kondisi ini berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu resistensi sosial dalam bentuk protes maupun penolakan. Islam mengingatkan bahwa kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan pada akhirnya akan merusak tatanan sosial dan melemahkan fondasi negara.
Dalam konteks kontemporer, gelombang demo menolak kenaikan PBB-P2 dapat dibaca sebagai ekspresi politik sekaligus moral masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dinilai tidak adil. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa rakyat tidak menolak kewajiban berkontribusi bagi pembangunan, tetapi menuntut agar kebijakan tersebut dijalankan dengan lebih arif, proporsional, dan berpihak pada kondisi nyata mereka. Di sinilah letak relevansi ajaran Islam, yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk pajak, harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pajak tidak boleh menjadi beban sepihak, tetapi harus dipandang sebagai instrumen kolektif untuk menjaga kesejahteraan bersama.
Islam sejak awal mengajarkan pentingnya shūrā atau musyawarah dalam perumusan kebijakan. Prinsip ini memberi ruang partisipasi rakyat agar suara mereka tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kenaikan PBB-P2, shūrā dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui dialog, sosialisasi, dan kajian yang terbuka sebelum menetapkan tarif baru. Tanpa adanya musyawarah, kebijakan akan kehilangan legitimasi moral meskipun sah secara hukum positif. Legitimasi moral inilah yang menjadi landasan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Jika suara rakyat diabaikan, kebijakan fiskal akan berhadapan dengan resistensi yang berkelanjutan. Demonstrasi, penolakan, bahkan potensi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak merupakan konsekuensi logis dari hilangnya rasa keadilan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga merusak nilai persaudaraan sosial yang semestinya dijaga. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dijalankan bukan dengan pendekatan koersif, melainkan dengan pendekatan persuasif yang menumbuhkan kesadaran kolektif. Dengan begitu, pajak akan diterima sebagai kewajiban moral sekaligus kontribusi sosial.
Demo PBB-P2 seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai koreksi sosial yang bernilai konstruktif. Masyarakat yang turun ke jalan sebenarnya sedang menyuarakan kebutuhan agar pemerintah lebih transparan, adil, dan peka terhadap kondisi mereka. Jika aspirasi ini ditanggapi dengan bijak, pemerintah dapat menjadikannya momentum untuk mengevaluasi kembali desain kebijakan fiskal, menyesuaikan tarif pajak dengan daya beli rakyat, serta memastikan bahwa hasil pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik. Dengan cara ini, pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai beban, tetapi sebagai sarana membangun kepercayaan dan solidaritas sosial.
Lebih jauh lagi, Islam memandang amanah fiskal sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan pajak, tetapi juga memastikan penggunaannya berorientasi pada pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif berarti hasil pajak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ketika masyarakat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, resistensi sosial akan berkurang, dan kepercayaan publik akan tumbuh. Hal ini sesuai dengan maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap harta, kehidupan, dan kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu, aspirasi rakyat melalui demo PBB-P2 perlu dipandang sebagai panggilan moral untuk kembali pada nilai dasar keadilan dan musyawarah. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengubah dinamika ketegangan menjadi momentum rekonsiliasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, kepercayaan akan pulih, dan kebijakan fiskal akan mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Islam mengajarkan bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kepercayaan rakyat, bukan sekadar pada instrumen hukum.
Akhirnya, pesan utama dari perspektif Islam adalah bahwa pajak bukan semata-mata instrumen fiskal, tetapi juga instrumen moral untuk menjaga keseimbangan sosial. Pajak yang adil akan mengurangi kesenjangan, memperkuat rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, pajak yang memberatkan hanya akan melahirkan gejolak sosial dan ketidakpuasan yang meluas. Dengan demikian, demo PBB-P2 menjadi refleksi penting bahwa rakyat mendambakan sistem perpajakan yang berpijak pada keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam yang menekankan kesejahteraan bersama.